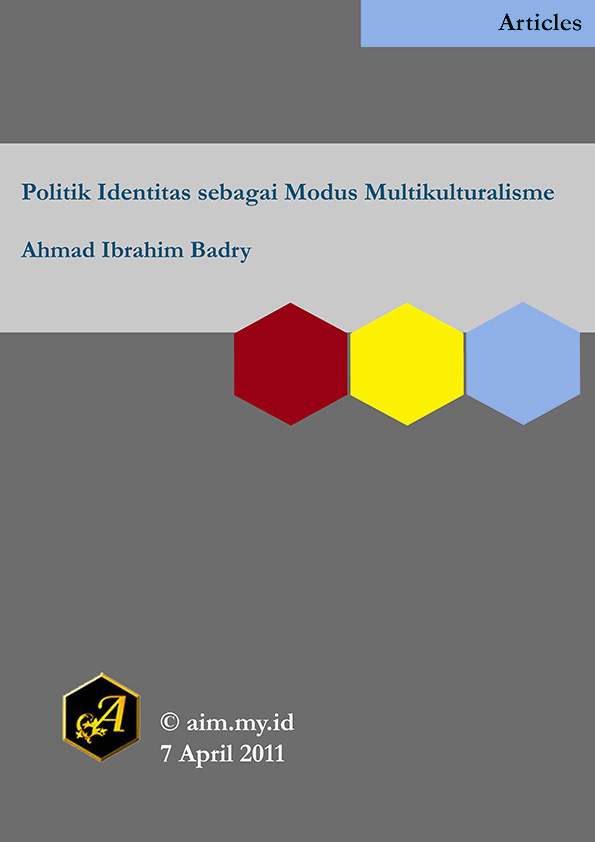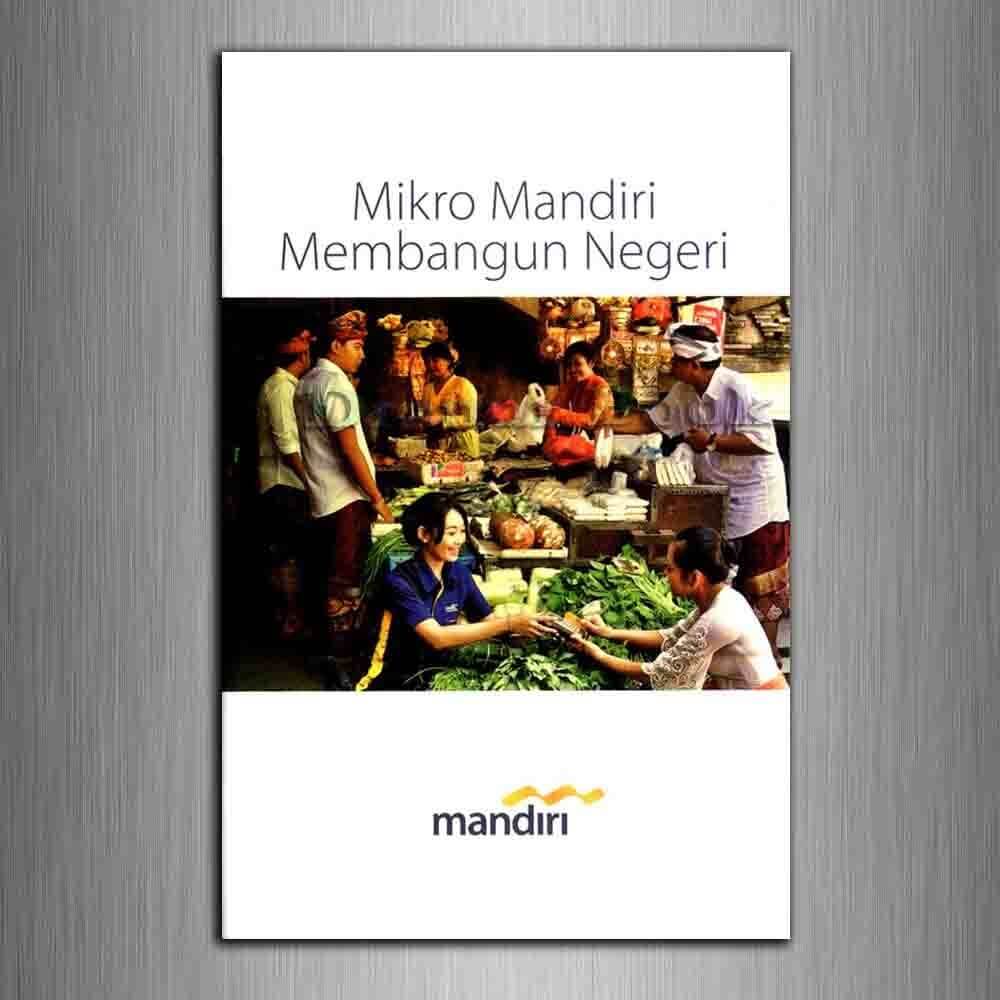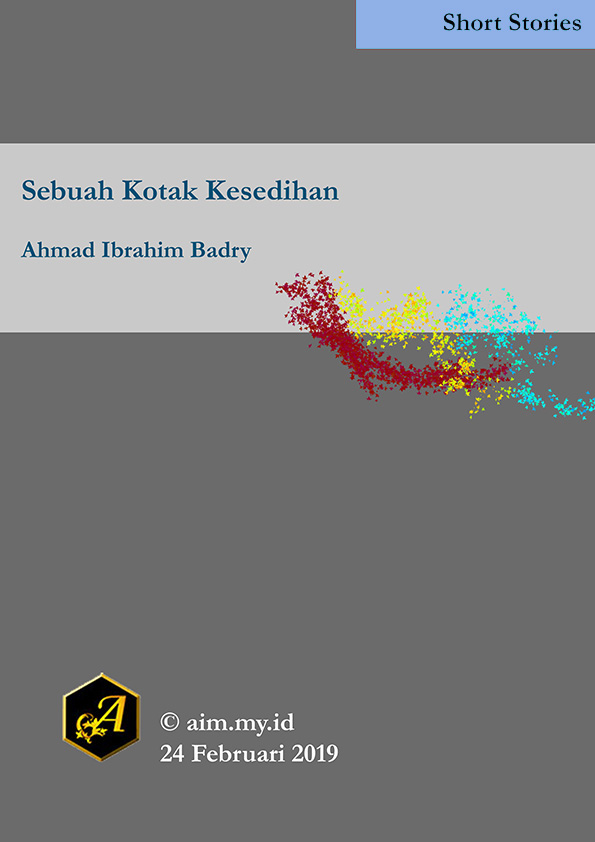The Salt of the Earth (2014) adalah film yang dibuat oleh Wim Wenders dan Juliano Ribeiro Salgado. Aslinya, film ini berbahasa Perancis dengan judul Le Sel de la Terre atau berarti Garam Dunia. Ia memuat kisah seorang pelukis cahaya, Sebastião Salgado. Lahir di Brasil, Sebastião merupakan potret dari seorang yang terpanggil memenuhi apa yang membuncah dalam dirinya. Ia menjadi kisah yang luar biasa di mana ribuan foto pada akhirnya lahir sebagai gambar rasa banyak manusia. Ada keceriaan, keramahan, ketenangan, kesedihan, kepiluan, ketidakpedulian, kebrutalan, kekejian, ketakutan, dan pada akhirnya harapan bahwa semuanya akan menjadi baik kembali. Ini adalah sebuah perjalanan menyelami relung terdalam manusia sekaligus mengabadikannya.
Menikmati kisahnya ini bukan sekadar puas dalam asupan visual sinematik ataupun tergetar dalam momen-momen heroik ala cerita dari bukit Hollywood. Menikmatinya adalah menjadi paham dan sekaligus menyelami rasa pergulatannya akan kemanusiaan. Dalam satu kisahnya, ia sanggup menjalani tidur di lantai semen pada rumah dengan ketinggian ribuan kaki di atas laut, pada daerah Oaxaca, Meksiko. Pengorbanannya ini dilakukan untuk dapat diterima oleh komunitas petani Mixe yang mengagungkan musik dalam kehidupannya. Atau, di kisah lainnya, ia sanggup untuk bertahan untuk mengabadikan rakyat yang kelaparan di daerah Ethiophia, atau Mali, atau Sahel di Afrika. Ia respek dengan semua momen penderitaan itu atau menjadi terkagum dengan figur bocah yang hidup berkelana sendirian di tengah tandusnya gurun. Bocah tegar itu pergi sembari membawa peralatan masak, gitar, bahkan tanpa celana, dengan hanya ditemani anjingnya.
Meskipun tampak berhasil dengan semua karyanya itu, ia tidak menjadi bangga karenanya. Ia sebenarnya sakit. Ia alami sakit hingga ke relung-relung jiwanya. Dengan peristiwa konflik yang terjadi di Rwanda saat tahun 1995, jutaan orang harus mengungsi ke Kongo. Ia pun mendapati 250.000 orang hilang dalam perjalanan mengungsi dan akhirnya habis terbunuh di Kisangani, Kongo, pada tahun 1997. Ia menjadi masygul dengan semua kenyataan ini, termasuk pada genosida sebelumnya di Yugoslavia. Tidak akan ada yang tahu bahwa ia mengabadikan semuanya ini dalam pergulatan kesedihan. Ia menangis setelah memberanikan diri memotret mereka, lalu berlaku seperti itu berulang kali dalam pengakuannya.
Pada akhirnya, panggilan alam jualah yang menyelamatkan jiwanya. Ketika Ayahandanya mulai sakit, ia dan keluarganya kembali ke Brasil. Namun, peternakan yang dikelola Ayahandanya waktu itu sudah menjadi lahan kering karena kehilangan hutan yang mengelilinginya. Istrinya, Lélia Wanick Salgado, mengajak Sebastião untuk menanam kembali. Lalu, keluarga Salgado dan orang-orang lainnya turut menanami hutan tandus itu dengan jutaan pohon. Dalam satu dasawarsa, tempat itu menjadi Instituto Terra yang akan menjadi bagian dari hutan lindung di Brasil di masa sekarang ini.
Dengan pengalaman akan kehijauan ini, Sebastião menjadi sangat dekat dengan alam. Pada awalnya, ia memikirkan satu proyek fotografi yang berhubungan dengan perusakan lingkungan. Namun, gagasan ini ditanggalkannya. Hatinya lebih suka dengan ekspresi hormat atas alam. Genesis (2004-2013) adalah karya besarnya di soal ini. Pengabdian itu muncul sekali lagi, namun berada di ujung garis yang berbeda.
Antara kemanusiaan dan kealaman adalah dua hal yang menjadi sentral dalam karya Sebastião. Dari dirinya, kita dapat belajar bahwa kemanusiaan dapat jadi memuakkan ketika jatuh dalam sisi yang paling gelap atas nama apapun. Tidak ada lagi penghormatan atas sesama yang bahkan lebih keji dari seekor serigala. Homo homini lupus seperti dikemukakan Hobbes itu keliru karena serigala tak akan membunuh kawananannya. Ketika perebutan kekuasaan terjadi untuk menjadi yang terkuat dalam kelompoknya, serigala yang kalah tidak akan terbunuh dan hanya akan menyingkir mencari tempat baru. Beda dengan manusia, yang kalau diperlukan, ketika ubun-ubun sudah panas oleh haus kekuasaan, jutaan orang tak bersalah dapat terbunuh sia-sia.
Namun, ketika engkau memuja alam dengan segala isinya, berkah itu akan datang menghampirimu. Alam akan menunjukkan siapa yang berbuat kebaikan akan mendapat ganjaran setimpal sebagaimana ditunjukkan oleh Sebastião beserta keluarga dan tetangganya. Akhirnya, mereka mendapatkan kesejukannya kembali dari tanah tandus tak berperi. Boleh jadi, air terjun di masa kecilnya yang hilang pun akan kembali di masa datang. Selain itu, Sebastião sekali lagi memperlihatkan bahwa kita hanya bagian kecil dari alam sebagaimana hewan lainnya dalam Genesis. Ekspresi hewan-hewan itu sekuat ekspresi manusia dan ingin menunjukkan bahwa mereka juga hidup serta layak untuk dihargai kehidupannya.
Dalam kenyataannya, manusia itu hanya seperti gumpal garam yang ingin memberi rasa pada lautan. Tidak ada gunanya pongah karena sudah dapat membuat gedung pencakar langit melebihi pohon ribuan tahun. Sekejap saja, ia akan hilang oleh gempa atau tsunami. Tidak perlu merasa digdaya karena sudah dapat mengirimkan roket ke Mars melampaui terbangnya burung bermigrasi ribuan mil. Sekejap saja, roket itu dapat hancur oleh tabrakan asteroid atau lenyap ditelan badai debu. Tidak usah merasa hebat karena sakti mandraguna melebihi kekuatan besi atau batu. Sekejap saja, pandemi karena virus membuatmu kelabakan tak tahu apa yang harus dilakukan dan berlindung dengan penuh cemas.
Belajar dari Sebastião, kita mungkin akan lebih baik menjadi garam untuk sepiring sambal atau semangkuk bubur. Ini memang tidak akan menjadi heroik sebagaimana Kapten Amerika atau Iron Man. Kalau Anda memilih menjadi pahlawan sih terserah. Tetapi, dunia akan menjadi lebih berwarna ketika ada sepiring sambal di hidangan atau semangkuk bubur sebagai sarapan di pagi hari. Terima kasih Sebastião untuk pengabdian sejatimu. Karya-karyamu akan menjadi warna abadi tentang perjalanan dan transformasi manusia yang sesungguhnya.
Depok, 23 Juli 2020
Image taken from IMDb