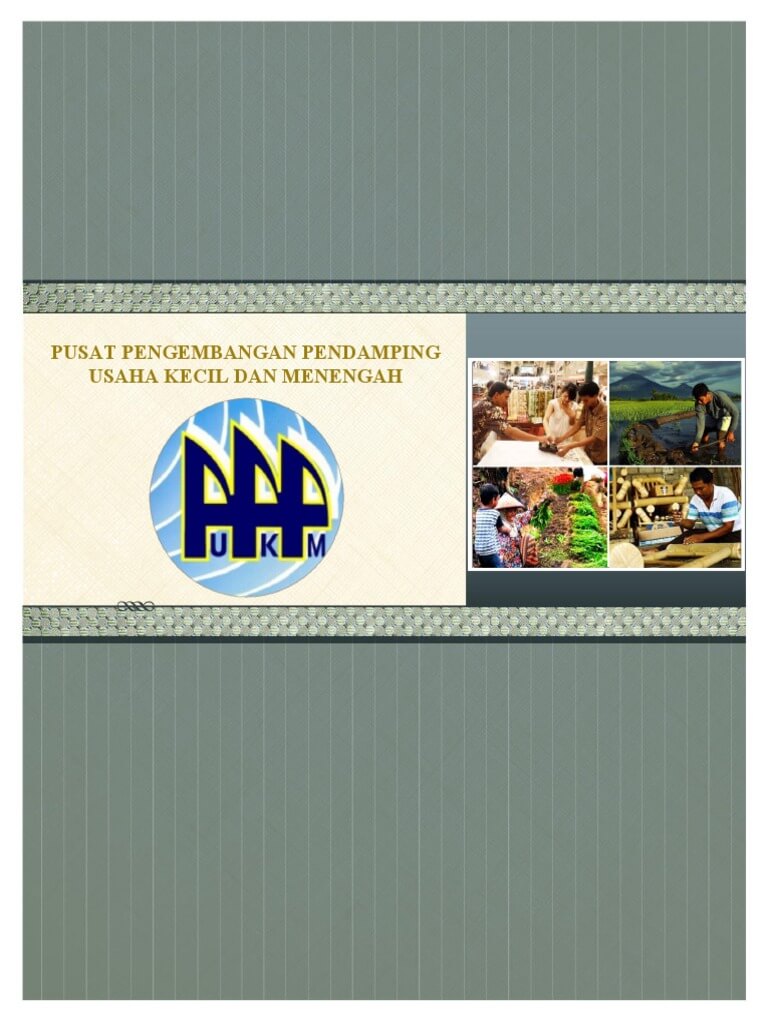Nadiem Makarim dan Program Merdeka dalam Sistem Pendidikan
Mengikuti sepak terjang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, Nadiem Makarim, saya merasa optimis bahwa dunia pendidikan di Indonesia akan berubah banyak hingga tingkat yang mendasar. Alasannya ada dua, yaitu: yang utama itu karena beliaunya masih muda dan mau belajar, serta yang berikutnya diawali oleh program Merdeka Belajar yang dicetuskannya. Ada empat aspek yang dibidik oleh program ini, yaitu (1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), (2) Ujian Nasional (UN), (3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan (4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi (Kemdikbud, 11 Desember 2019). Dari keempat aspek tersebut, meskipun banyak orang lebih menyoroti soal dihapuskannya UN atau RPP yang hanya 1 halaman dengan pro dan kontra, hal yang lebih krusial justru terletak pada penetapan Asesmen Kompetensi Minimum sebagai model Asesmen Pengganti UN. Aspek inilah yang ingin saya tinjau karena berhubungan langsung dengan modal dasar dalam pengembangan pendidikan Indonesia di masa depan.
Dalam hal Asesmen Kompetensi Minimum, Nadiem memilih Literasi, Numerasi, dan Karakter. Tentu saja, alasan pemilihannya itu sangat rasional. Hal ini mengacu pada standar penilaian kompetensi siswa di dunia, seperti Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), atau Programme for International Student Assessment (PISA). TIMSS Ini dimulai dari tahun 1995 dan berjangka waktu 4 tahun. Tujuannya adalah mengukur pencapaian matematika dan sains seorang siswa usia 10 dan 14 tahun. Ia juga meliputi telaah bagaimana dukungan orangtua, sikap siswa, kurikulum, pelatihan guru, dan aktivitas di kelas mempengaruhi kompetensi siswa di kedua bidang ini. Untuk PIRLS, ini dimulai dari tahun 2001 dan berjangka waktu 5 tahun. Tujuannya adalah menguji pemahaman membaca seorang siswa usia 10 tahun. Studinya juga mencakup bagaimana siswa itu diajarkan membaca di rumah maupun di sekolah. TIMSS dan PIRLS dicetuskan oleh IEA. Khusus untuk PISA yang dicetuskan oleh OECD, surveinya dimulai pada tahun 2000 dan berjangka waktu 3 tahun. Tujuannya adalah menguji kemampuan pengetahuan siswa usia 15 tahun dalam menghadapi situasi kehidupan nyata. Ini menjadi sejenis evaluasi sistem pendidikan yang diterapkan di berbagai negara (Cambridge Assessment International Education, 2017).
Dengan mengacu pada standar penilaian kompetensi siswa tingkat dunia, Nadiem tentu saja ingin agar siswa Indonesia dapat meningkat kadar kompetensinya. Oleh karena itu, ia mencukupkan diri hanya pada kompetensi minimum, mengingat ini sekaligus kompetensi inti untuk penguasaan bidang apa pun. Itulah yang dijelaskannya saat Rapat Dengar Pendapat di DPR pada 12 Desember 2019. Meskipun begitu, dalam ketiga standar penilaian siswa tingkat dunia tersebut, hanya kompetensi Literasi dan Numerasi yang diukur. Lalu, kenapa Karakter juga dimasukkan ke dalam Asesmen Kompetensi Minimum?
Jawaban atas pertanyaan tersebut, mengikuti uraian Nadiem, merupakan survei atas pendidikan nilai, terutama nilai yang berdasarkan Pancasila. Yang ia bayangkan, siswa tidak hanya belajar soal menghafal Pancasila atau ajaran soal pengamalan Pancasila sebagaimana dulu dirumuskan oleh BP7 di masa Orde Baru. Siswa akan disurvei mengenai pengalamannya atas situasi sekelilingnya. Misalnya, apakah ia mendapatkan perundungan (bully) dari pihak lain yang melanggar sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, atau apakah ia diajarkan nilai intoleran yang justru bertolakbelakang dari sila Persatuan Indonesia.
Meskipun akan diarahkan Nadiem pada evaluasi pendidikan nilai Pancasila berikut pengalamannya, saya justru melihat kategori Karakter lebih daripada sekedar evaluasi. Hal ini karena yang disurvei adalah anak didik yang memang hendak dibentuk Karakternya, bukan seseorang yang cenderung terbentuk Karakternya. Survei Karakter, oleh karenanya, akan menjadi sarana untuk identifikasi bakat, kecenderungan, dan pengalaman siswa itu sendiri. Jika merujuk pada aspek kognitif, ini dapat diidentifikasi melalui IQ. Akan tetapi, aspek kognitif itu sendiri sudah diwakili oleh survei Literasi dan Numerasi, di mana IQ menjadi alternatif dari TRIMSS, PIRLS, atau PISA bagi siswa dengan usia 16 tahun ke atas. Yang belum menjadi jelas di sini adalah bagaimana survei Karakter itu akan dilaksanakan karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru akan menerapkannya di tahun 2021.
Survei Karakter sebagai Pemetaan dan Pengembangan Kecerdasan Emosi
Bercermin pada pendidikan di Indonesia selama hampir tujuh belas tahun, saya melihat dengan mata seorang pendidik bahwa fokus di pendidikan dasar dan menengah adalah keterampilan mengingat. Jika bukan di sekolah bonafid, siswa itu sangat jarang diajak mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pengecualian dapat diberikan pada Guru Penggerak yang memang punya keinginan kuat untuk mengembangkan siswanya. Namun, Guru Penggerak seringkali jadi orang asing di tengah lingkungannya. Film Laskar Pelangi dengan jelas menceritakan suka duka Guru Penggerak dengan segala keterbatasannya.
Jika bercermin dari kisah Laskar Pelangi ini, kompetensi mengingat menjadi kemampuan dari Lintang yang memorinya sangat kuat dalam menghafal, mengolah perhitungan, dan berhasil dalam perlombaan cerdas cermat. Namun, perjalanan hidup tidak membuatnya menjadi seorang anak yang “berhasil” karena ia terpaksa meninggalkan sekolah demi menjadi pengganti orangtua dalam mengasuh adik-adiknya. Kisah Lintang ini berbeda dengan Ical. Ical menjadi seorang yang “berhasil” karena ia dapat mengendalikan emosi remajanya. Dari tukang kabur pada saat sekolah di tingkat menengah atas hingga berhasil diterima kuliah di Jakarta dan Paris, Ical tumbuh dengan kecerdasan emosi yang cukup menonjol. Keberhasilan ini tentunya tak lepas dari peran orangtua yang mendampinginya. Sementara, Lintang berjuang sendiri sejak kecil dan secara emosional tidak terdampingi dengan baik. Meskipun begitu, potensi Lintang yang kuat menjadikannya tetap “berhasil” sebagai orangtua karena ia dapat bercermin ke belakang.
Di sisi ini, pelajaran berharga yang kadang dilupakan adalah perjalanan seorang anak dalam hidup dan berhadapan dengan lingkungannya itu sendiri. Ia bukanlah semata perjalanan mengingat. Ia adalah perjalanan emosional karena anak adalah manusia yang sangat peka. Pada perjalanan di usia dini hingga remaja, anak terbentuk emosinya. Boleh jadi, ia akan “mengingat” cukup kuat perjalanan emosinya tersebut dan membentuknya menjadi siapa dirinya sekarang ini.
Melalui pemahaman serupa ini, survei Karakter menjadi sesuatu yang penting untuk dilaksanakan. Bukan saja ia akan berlaku sebagai pemetaan atas Kecerdasan Emosi serupa apa yang terbentuk pada seusianya, tetapi juga dapat menjadi panduan bagi orangtua dalam membimbing putra-putrinya. Kita tidak ingin anak-anak kita menjadi psikopat tentunya. Dalam kasus yang baru-baru ini viral di awal Maret 2020, seorang anak remaja berinisial NF tampak memiliki kecenderungan “psikopat” saat ia dengan paras dingin menceritakan bahwa dirinya telah membunuh bocah usia 6 tahun. Orangtuanya pun kaget dengan kenyataan ini. Perjalanan emosi putri remajanya ternyata “sangat mengejutkan”.
Kasus tersebut dapat jadi contoh betapa kita sebagai orangtua tetap tidak dapat “mengetahui sepenuhnya” perjalanan emosi seorang anak yang mungkin saja rentan dan tidak sekuat Lintang dalam Laskar Pelangi ketika menjalani kehidupannya. Survei Karakter di pendidikan dasar oleh karenanya menjadi sesuatu yang tak dapat kita abaikan. Di sisi ini, oleh karena hal tersebut belum terlaksana, perlu dirumuskan dengan cara sebaik mungkin soal dan materi Kecerdasan Emosi apa yang perlu disurvei pada seorang anak. Sehingga, emosi yang mengarah pada yang negatif dan dingin dapat diidentifikasi secara dini dan dapat diterapi secepatnya. Hal ini juga akan membantu pengarahan anak secara lebih baik pada jenjang pendidikan menengah.
Model Kecerdasan dalam Konteks Industri 4.0
Berbeda dengan fokus di pendidikan dasar dan menengah, fokus di pendidikan tinggi sedikit lebih rumit. Hal ini karena kita berhadapan dengan orang dewasa yang memiliki pikiran, keinginan, dan ambisi yang berbeda-beda skalanya. Dengan segala keunikannya, manusia dewasa dapat dipastikan tumbuh dengan Karakter yang berasal dari tempaan masa kecil dan remaja sebagaimana tadi telah disinggung.
Meskipun rumit, di konteks pendidikan tinggi, Nadiem mengusulkan program sederhana, yaitu Kampus Merdeka. Ia menginginkan mahasiswa agar dapat belajar di luar kampusnya selama 3 semester. Dalam salah satu wawancara pada siaran podcast di YouTube yang diusung oleh Deddy Corbuzier, Nadiem mengatakan bahwa pilihan tersebut seibarat perjalanan manusia yang akan terjun di laut. Mahasiswa perlu mengenali lautnya terlebih dahulu sebelum benar-benar mencebur ke dalamnya. Contoh ini mengandaikan adanya pengalaman langsung. Mahasiswa kalau hanya belajar di satu perguruan tinggi saja akan serupa dengan katak dalam tempurung. Ia akan miskin dengan pengalaman dan tidak luas orientasi keilmuannya.
Mahasiswa seperti inilah yang saya temui, bahkan di level perguruan tinggi sekelas Universitas Indonesia. Ketika mahasiswa dari jurusan teknik diajarkan ilmu sosial, mereka kebingungan karena ternyata manusia atau masyarakat dapat dipahami dengan cara yang berbeda-beda dan tidak tunggal. Begitupun sebaliknya, ketika mahasiswa bidang sosial diajarkan soal perspektif kritis atas teknik, mereka menjadi bingung karena merasa tidak ada yang salah dengan aspek teknikal yang mereka hadapi dalam keseharian. Apa yang salah dengan telepon pintar yang membantu saya dalam pekerjaan? Padahal, dengan nyalanya “on location” di telepon pintarnya, data dirinya dapat terlacak dan dapat digunakan oleh orang yang tak berhak dan berpikiran kriminal. Aspek pemahaman yang menyatukan antara bidang sosial dan teknik menjadi lepas dari perspektif mahasiswa. Padahal, perspektif tersebut dapat menjadi sarana utama dalam memahami konsekuensi dari Revolusi Industri 4.0.
Jika menelaah lebih jauh Industri 4.0, ia akan memiliki fondasi pada apa yang dinamakan Cyber Physical System (Sistem Siber Fisik). Istilah ini sendiri berarti gabungan dari nanoteknologi, bioteknologi, teknologi informasi dan komunikasi, dan sains kognitif. Apa yang sedang kita lihat sekarang adalah baru masuk dalam tahap I, di mana sains kognitif tergabung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang menghasilkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence). Pada kecerdasan buatan, pembelajaran mesin (machine learning) dan pembelajaran mendalam (deep learning) menjadi garda depan teknologinya. Hasilnya, Sophie si robot cerdas dapat diakui menjadi warga negara di Saudi Arabia (Kompas.com, 2017).
Relevansi diskusi kita atas gagasan Kampus Merdeka ala Nadiem dengan konteks Industri 4.0 sebenarnya menjadi sesuatu yang paralel. Jika mesin saja sekarang sudah masuk dalam pembelajaran mendalam, masa pembelajaran manusia itu melulu monoton sifatnya? AlphaGo yang menjadi proyek dari Google DeepMind menjadi salah satu contoh bagaimana jutaan peluang dapat dipelajari dan dikalkulasi dengan baik oleh sebuah mesin. Ketika pertandingan Go dilaksanakan pada 8-15 Maret 2016 antara AlphaGo dengan Lee Sedol di Korea Selatan, hasilnya membuat publik dunia terhenyak karena Sedol hanya mampu mencuri 1 kemenangan saja (AlphaGo, 2017).
Dua contoh mesin cerdas, Sophie dan AlphaGo menunjukkan bahwa manusia tidak dapat semata bertumpu pada kecerdasan kognitif untuk dapat memperoleh tempat dan pekerjaan di masa sekarang dan masa depan. Yang sekarang diperlukan dunia, menurut World Economic Forum, adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks (Future Job Reports, 2016).
Refleksi dan Pentingnya Informasi Akurat untuk Pemanfaatan Peluang
Dari apa yang telah disampaikan, tampak bahwa pekerjaan rumah bagi seorang pendidik teramat besar saat ini. Untuk sementara, Thomas M. Nichols benar ketika ia mengatakan bahwa kepakaran itu sudah mati dalam bukunya yang berjudul The Death of Expertise (2017). Hal ini terjadi ketika banyak suara ahli tidak didengar oleh masyarakat. Ketika banyak yang lebih percaya pada berita hoaks daripada pernyataan seorang ahli, apa yang dikumandangkan Nichols menjadi lebih bergema adanya. Selain itu, jika apa yang disampaikan guru atau dosen tidak lebih baik daripada konten Google, maka sekali lagi Nichols menjadi benar perkataannya.
Namun demikian, sejalan dengan keprihatinan Nichols, buat saya pribadi, kepakaran itu ada pentingnya. Tanpa adanya kepakaran, kita tidak akan pernah tahu apa yang hendak diperbuat oleh para penguasa sains dan teknologi di luar sana. Mereka yang menguasai informasi tertentu punya kecenderungan untuk memanipulasi orang yang tidak tahu demi kepentingannya. Misalnya saja, ketika tukang ojek menawarkan harga tak masuk akal ketika penumpang membutuhkan tumpangan sepeda motornya, ini adalah contoh bagaimana manipulasi informasi terjadi pada tingkat terbawah. Bayangkan, jika seorang Professor atau CEO perusahaan teknologi yang melakukan itu, informasi seperti apa yang disembunyikan oleh mereka? Hal ini dapat saja berkaitan dengan apa yang mungkin tidak kita ketahui tentang bagaimana jalannya kehidupan ini akan dibawa ke mana. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks Revolusi Industri 4.0, jika kita tidak benar-benar mendapatkan informasi yang akurat di soal ini, apakah para pendidik akan mampu menyiapkan para siswa atau mahasiswanya?
Pada sisi ini, Nadiem mendapat tantangan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana membuat kebijakan yang baik dalam soal identifikasi Karakter pada pendidikan dasar dan menengah, namun ia perlu sekaligus menjajagi kemungkinan antisipatif atas konteks Industri 4.0 bersama dengan munculnya masalah ketika kepakaran tidak lagi dipercaya sepenuhnya di masyarakat. Masa depan dunia pendidikan Indonesia akan ditentukan dari bagaimana keputusan atas soal ini dibuat secara komprehensif dan bukan semata-mata mempermudah soal administratif saja. Soal pendidikan bukanlah soal yang ada di atas kertas belaka, tetapi menyangkut hati dan pikiran anak-anak sebagai generasi penerus kita.
Selain itu, dari kasus pertandingan Go di atas, kita juga dapat belajar bahwa Sedol boleh saja kalah menghadapi AlphaGo. Akan tetapi, ia tidak pernah menyerah hingga akhir. Ketika mesin semakin tambah pintar dan cerdas, satu-satunya peluang bagi kita sebagai manusia adalah memperkaya pengalaman diri kita dengan terus menerus belajar. Peluang 1% pun akan menjadi sangat berharga sebagaimana Sedol memanfaatkannya untuk mengalahkan AlphaGo. Dalam konteks ini, kemampuan memanfaatkan peluang 1% inilah yang perlu terus menerus dikembangkan sebagai modal bagi kita untuk bertumbuh dan semakin matang menghadapi tantangan. Modal dari ini semua bertumpu pada kegigihan dan harapan, sesuatu yang mungkin belum dimiliki oleh mesin pada saat sekarang ini tetapi dimiliki oleh kita sebagai manusia.
Depok, 10 Maret 2020/1 Agustus 2020
Unduh artikel/esai ini dalam bentuk pdf