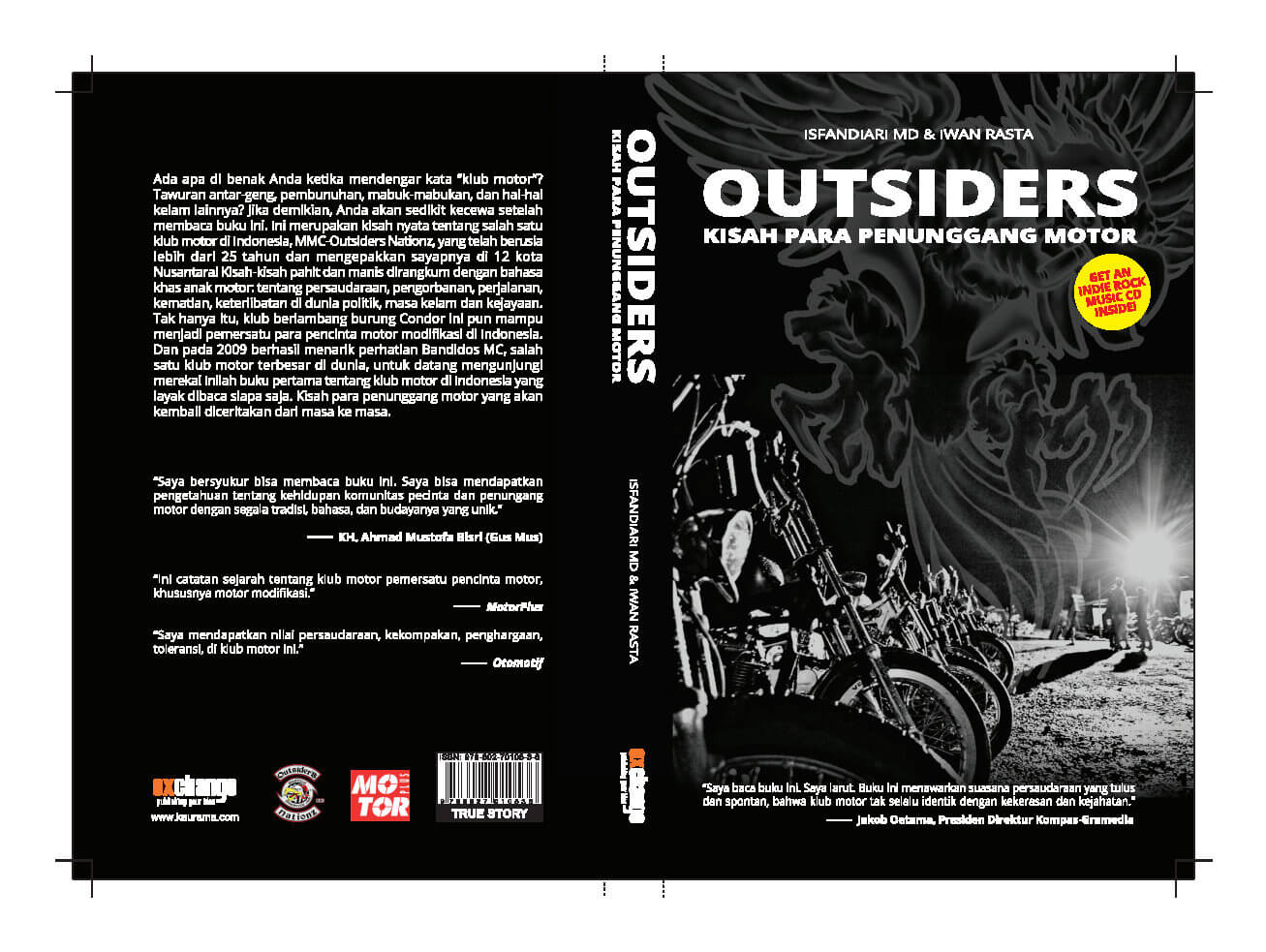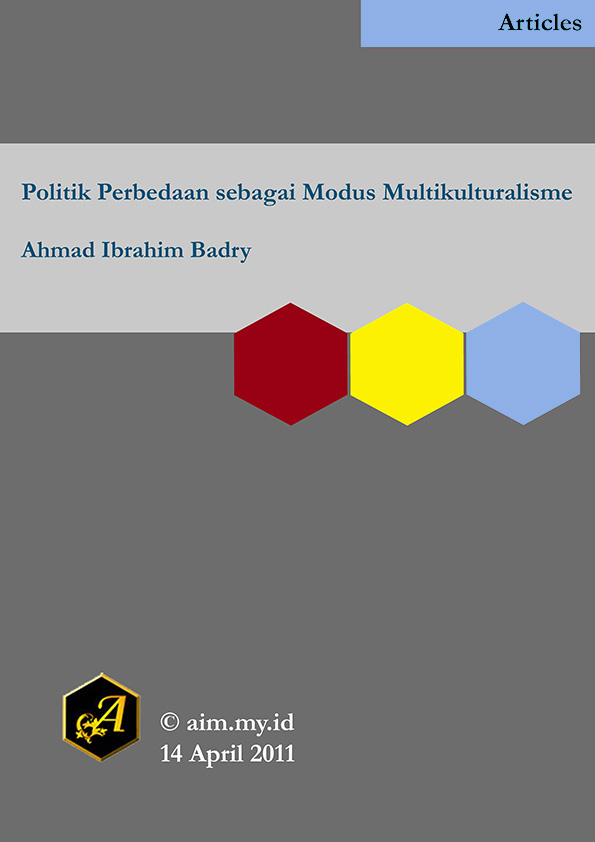Kontroversi Chat GPT di Lingkungan Pendidikan
Dalam perkembangan terkini di bidang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), fenomena Chat GPT yang dikembangkan oleh OpenAI cukup menggemparkan khalayak akademik. Mereka khawatir bahwa aplikasi tersebut akan menjadi cara baru dari murid atau mahasiswa/i untuk berbuat curang pada saat diberikan ujian, baik itu yang sifatnya ujian dapat membaca buku (open book exam) atau pekerjaan rumah (homework). Bahkan, kecurangannya dapat dikatakan lebih jauh daripada sekadar metode copy – paste yang menggunakan informasi dari internet karena Chat GPT dapat menghasilkan esai utuh yang cukup baik, serta lolos dari pengecekan piranti lunak Anti-Plagiarisme.
Hal inilah yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi Amerika Serikat belakangan. Bahkan, menurut informasi yang disampaikan oleh Danny Oppenheimer dari Carnegie Mellon University, koleganya terlihat panik ketika mereka bercerita bahwa Chat GPT dapat mengerjakan ujian jarak jauh (remote exam) yang diberikan kepadanya dan mendapat skor sempurna. Namun demikian, Oppenheimer juga bilang bahwa kecurangan model Chat GPT tidak lebih dari sekadar satu jenis kecurangan baru yang lebih murah karena penggunaan Chat GPT yang masih gratis. Di sekitaran kampus yang pernah ia bergabung, ada banyak selebaran yang dibuat oleh para Kandidat Doktor bagi calon sarjana yang memerlukan bantuan dalam ujian-ujian seperti ini. Kandidat Doktor tersebut melakukan ini dalam rangka menutupi kekurangan biaya hidup dari beasiswa yang mereka dapatkan. Berdasarkan pengalaman tersebut, Oppenheimer menyimpulkan bahwa kita tidak perlu panik berhadapan dengan Chat GPT karena mahasiswa/i akan selalu menemukan cara kalau mereka ini memang berniat curang (Times Higher Education, 17 Januari 2023).
Beberapa institusi pendidikan Amerika Serikat, dalam berita yang disampaikan oleh CBC, bahkan bergerak lebih jauh dari sekedar panik. Di tingkat pendidikan menengah, misalnya Seattle Public Schools, mereka memutuskan untuk memblok penggunaan Chat GPT. Di luar Amerika Serikat, institusi ternama pendidikan Perancis, Sciences Po, juga melakukan hal yang sama dengan keputusan pelarangan Chat GPT digunakan dalam ujian-ujian mereka. Ini menjadi kontroversi dan debat yang cukup panas di lingkungan akademisi dan pendidik. Dalam konteks ini, pihak OpenAI sendiri tidak berusaha untuk menyelesaikan debatnya. Mereka hanya bilang melalui periset kebijakannya, Lama Ahmad, bahwa Chat GPT itu boleh disikapi dengan cara apa pun sesuai nilai atau prinsip yang pengguna miliki. Pihak OpenAI hanya memberikan informasi yang terbaik soal platform ini untuk pengguna pahami dan dipersilahkan mengambil keputusan yang terbaik atas Chat GPT (CBC News, 31 Januari 2023).
Dalam kaitannya dengan soal kecurangan akademik ini, kita ternyata lebih melihat bahwa masalahnya ada pada jenis cara yang dilakukan daripada bertanya kenapa ini dilakukan? Perhatian atas jenis caranya dan rasa panik menunjukkan bahwa banyak dari pengajar di Universitas lebih memiliki fokus pada pengujian kapasitas kognitif mahasiswa/i daripada berusaha mendorong mahasiswa/i untuk belajar aktif secara mandiri. Dalam hal yang kedua, para pengajar mungkin tidak punya banyak waktu yang memadai. Ini karena untuk dapat melakukan hal tersebut, relasi antara mahasiswa/i dan dosen harus terbangun dengan cukup baik sebelumnya.
Hal ini seperti terlupakan dalam banyak pengajaran di Universitas, terutama pada dosen yang memandang bahwa mahasiswa/i itu tidak memiliki kapasitas kognitif dari mata kuliah yang diasuhnya dan lupa kalau mahasiswa/i juga punya ruang akses yang sama atas informasi yang dosen bisa dapatkan. Ketika soal yang diberikan hanya sama saja dengan soal yang diberikan pada 5 tahun lalu, inilah yang problem. Yang jadi masalah di sini adalah bukan Chat GPT-nya sebagai alat untuk melakukan kecurangan, namun soal ujian dosen-nya lah yang perlu diupdate hingga ke referensi terkini.
Menyikapi hal tersebut, penulis ingin melihat bahwa ketika kita mendefinisikan kecurangan akademik ini perlu pembatasan yang jelas lebih dulu. Selain itu, kita juga perlu melihat bahwa apa sebenarnya fungsi dari Chat GPT dalam kehidupan akademik kita sekarang ini. Kedua aspek inilah yang penulis ingin coba cermati di bagian berikutnya. Selain itu, pertimbangan lain yang terkait dengan situasi dan kondisi dunia juga mesti menjadi perhatian kita dalam menyikapi fenomena tersebut.
Kecurangan Akademik dalam Kaitannya dengan Perkembangan Teknologi
Problem kecurangan dalam konteks akademik tidak hanya menjadi masalah kita di saat sekarang. Jika meniliknya pada sejarah manusia, ia memiliki akar historis yang cukup panjang. Dalam bukunya yang berjudul Cheating Lessons: Learning from Academic Dishonesty (2013), James M. Lang menunjukkan pada kita bahwa ini bermula dari lahirnya kompetisi di antara sesama manusia. Sebagai contohnya, Lang menyajikan bahwa kecurangan terjadi dalam kompetisi atletik ala Yunani Kuna yang disebut Olimpia dan menjadi cikal bakal Olimpiade masa kini, atau dalam kompetisi ujian untuk menjadi pejabat publik di seluruh wilayah Kerajaan Tiongkok pada abad ke-7 (2013, 19-22). Berkaca dari fakta historis tersebut, kita dapat mengatakan bahwa kecurangan telah menjadi sesuatu yang mengakar pada budaya kompetisi itu sendiri secara alamiah.
Orang akan mempertaruhkan segalanya untuk menjadi yang terbaik di antara sesamanya karena itu sepadan dengan pemenuhan ambisi dirinya dan hidup gemilang setelahnya. Apa yang diperjuangkan bukan hanya sekadar gengsi atau martabat, melainkan bagaimana menempatkan dirinya sebagai yang berkuasa. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang “lumrah” ketika berbagai cara ditempuh untuk mendapatkannya, termasuk melakukan kecurangan. Hal ini terjadi ketika sistem meritokrasi diciptakan. Bahwa yang terbaik dan yang memiliki kapasitaslah yang akan menjadi seseorang yang berada di posisi atas dan berkuasa.
Meskipun begitu, dalam konteks lingkungan akademik, kecurangan sebenarnya hanya akan terjadi ketika murid atau mahasiswa/i hanya dinilai menjadi yang terbaik dalam sistem scoring. Ini menjadi sesuatu yang umum diterapkan di hampir seluruh institusi pendidikan di dunia. Paradigma tersebut tidak berubah dalam 20 abad perjalanan umat manusia. Meskipun sistem ini telah melahirkan banyak akademisi/ilmuwan cemerlang, seperti dapat kita lihat dalam catatan sejarah, namun sistem ini tidak membawa penyelesaian atas persoalan penting umat manusia sebagaimana tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang dibuat oleh PBB.
Dari soal ini, kita dapat melihat bahwa ada yang keliru dalam sistem pendidikan kita itu sendiri. Untuk dapat menyelesaikan persoalan SDGs, kita tidak hanya mendasarkan diri pada aspek kompetitif, namun memerlukan aspek kolaboratif. Bagi orang yang terbiasa untuk kompetitif, aspek kolaboratif ini tentunya akan menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Padahal, kalau kita tengok dalam praktik kerja di banyak institusi (baik pemerintahan atau swasta), kerjasama antar anggota dalam institusi ini menjadi suatu prasyarat mendasar bagi berhasilnya program/proyek yang dicanangkan.
Apalagi kalau kita memerhatikan lajunya perkembangan teknologi yang begitu cepat. Hal ini semua tidak akan dapat tercapai dengan baik tanpa adanya kerjasama antar individu. Inilah dimensi kolaboratif yang memungkinkan para insinyur/ilmuwan untuk menciptakan alat atau teknologi yang dibutuhkan institusi atau masyarakat. Dalam konteks ini, ada dua karakter yang berbeda dalam pengembangan teknologi berbasis kerjasama. Pertama adalah pengembangan teknologi yang dihasilkan oleh kerjasama di antara anggota institusi yang sama. Teknologi serupa inilah yang dikembangkan oleh universitas, perusahaan, atau lembaga riset pemerintahan tertentu. Pada jenis pengembangan serupa ini, teknologi yang dihasilkan bersifat proprietary (berhak cipta secara mutlak dan tidak boleh diproduksi tanpa seizin institusi pengembang).
Sementara itu, yang kedua adalah jenis pengembangan teknologi yang menghendaki kerjasama tanpa keterikatan satu institusi yang sama. Ini dapat kita lihat pada platform pengembangan teknologi yang disebut open source (sumbernya terbuka dan memiliki unsur hak cipta yang tidak mutlak). Platform jenis ini menjadi popular dan menjadi alternatif dari pengembangan teknologi yang didasarkan pada kerja satu institusi saja. Selain itu, pengembang teknologi open source ini boleh mengubah dan mengembangkannya lagi sesuai kebutuhannya. Biasanya pengembangan teknologi lain yang didasarkan pada open source akan mencantumkan nama pengembang awalnya sebagai bagian dari penerapan hak cipta yang tidak mutlak.
Bila kasus kerjasama pengembangan teknologi ini diperhatikan, kita seharusnya dapat mengkaji kembali cara bagaimana kita menilai mahasiswa/i dan sistem evaluasi hasil belajarnya. Untuk beberapa kasus pengujian mahasiswa/i yang memang memerlukan keterampilan teknis tanpa penggunaan alat bantu, kita memang dapat sepakati bahwa hal ini adalah ujian untuk mengasah keterampilan teknis individunya. Misalnya saja ketika mahasiswa bidang sains/teknik diuji kemampuan berhitungnya, maka wajar saja jika penggunaan alat bantu, dari mulai kalkulator, smartphone, atau alat lainnya tidak diperbolehkan.
Namun demikian, bagaimana dengan pengujian bidang sosial/humaniora yang memang hendak menguji keterampilan berbahasa atau memahami? Apakah ini juga dapat diperlakukan sama dengan ujian keterampilan berhitung? Jawabannya dapat iya dan tidak bergantung pada kebutuhan dari dosennya itu sendiri sebenarnya. Ketika jawabannya iya, problem mendasar ada pada model asesmen evaluasinya. Ketika mereka diberikan tugas aktif mandiri dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat bantu, baik itu kamus, ensiklopedia, buku teks, mesin pencari, atau Chat GPT itu sendiri, bagaimana dosen ini akan menerapkan pola asesmen evaluasinya? Jika khawatir dengan pemakaian alat bantu, maka dosen dapat membuat ujiannya dalam pola yang tidak menggunakan open book, remote, atau homework dengan konsekuensi tiadanya model tugas aktif mandiri. Namun demikian, ini akan membawa konsekuensi lain bagi dosen karena harus menghadiri ujiannya langsung dan mengoreksinya pula tanpa alat bantu. Jika dosen mengoreksinya dengan alat bantu, hal tersebut juga menjadi tidak adil. Ini karena sementara mahasiswa/i tidak diperbolehkan, dosennya malah menyerahkan penilaiannya pada alat bantu.
Dalam uraian yang terakhir, dosen perlu bercermin pada dirinya dan menyadari bahwa asesmen evaluasi hanya berlaku saat itu saja. Selain itu, apa yang diandaikan benar oleh dosen melalui asesmen evaluasinya ini pun sebaiknya dipertimbangkan sebagai sesuatu yang tentatif saja. Ini karena perkembangan ilmu/teknologi dapat bergerak sangat cepat dan terjadi setiap saat di belahan dunia mana pun. Apa yang kita pikirkan sebagai hal yang baru, boleh jadi menjadi usang hanya dalam beberapa minggu atau malah dalam setengah hari saja.
Memerhatikan secara seksama apa yang telah disampaikan di atas, tentunya pemahaman atas kecurangan akademik akan berbeda pada setiap institusi akademik. Jika mementingkan keterampilan individu yang sifatnya spesifik, alat bantu apa pun akan tidak diperbolehkan. Namun demikian, ketika yang dipentingkan adalah aspek kompetitif dan kolaboratif sekaligus, alat bantu untuk penguasaan keterampilan tertentu menjadi sesuatu yang dapat dikata komplementer. Kalkulator dalam keterampilan berhitung, translator dalam keterampilan berbahasa, ataupun Chat GPT dalam pengembangan kreativitas berbasis pembelajaran mandiri akan dipandang sebagai suatu pelengkap dan bukan lagi ancaman terhadap kecurangan akademik.
Dalam kerangka perspektif yang terakhir, yaitu Chat GPT sebagai alat bantu yang komplementer, hal tersebut tidak perlu dianggap sebagai ancaman pula yang akan menghilangkan banyak pekerjaan manusia. Dalam soal ini, kalaupun kita anggap sebagai ancaman, ia akan lebih tepat mengancam seseorang yang merasa dirinya paling pintar secara akademik dan seringkali menganggap orang lain bodoh. Chat GPT akan menjadi counter bagi seseorang dengan ego yang narsistik di lingkungan akademik. Ini menandakan bahwa pada level Profesor pun, seseorang masih perlu belajar hingga akhir hayatnya.
Pada konteks ini, penulis teringat pada satu tayangan film biografis yang menarik dan mendidik. Kebrilianan sekelompok perempuan kulit hitam Amerika yang bekerja di NASA menjadi tema film tersebut. Hidden Figures (2017) adalah sebuah kisah yang memperlihatkan bagaimana aspek kompetitif dan kolaboratif sekaligus. Katherine Goble Johnson, Dorothy Vaughan, dan Mary Jackson adalah perempuan-perempuan cerdas sekaligus ambisius yang memiliki prestasi ciamik dalam bidang sains/teknologi. Johnson sendiri adalah ahli matematika yang luar biasa dan mampu melakukan perhitungan secara cermat, tepat, sekaligus akurat tanpa banyak menggunakan alat bantu. Ia menjadi satu-satunya perempuan kulit hitam anggota Space Task Group di bawah pimpinan Al Harrison yang melakukan riset tentang bagaimana meluncurkan pesawat antariksa ke luar bumi. NASA waktu itu berkompetisi dengan badan antariksa Uni Sovyet yang meluncurkan Kosmicheskaya Programma SSSR (Program Ruang Angkasa Sovyet) dan sudah berhasil meluncurkan pesawat ke ruang angkasa beserta satelit bernama Sputnik dan Zenit.
Sementara itu, Jackson adalah insinyur yang membantu perancangan penahan panas pesawat antariksa. Ia bahkan harus bersekolah lagi di sebuah perguruan tinggi yang rasis terhadap kaum kulit hitam setelah menang di pengadilan yang memperbolehkan ia untuk mengambil studinya ini. Beda dengan Johnson dan Jackson, Vaughan adalah supervisor dari sekelompok perempuan kulit hitam yang melakukan perhitungan manual atas data yang diperlukan dalam riset pesawat antariksa ini. Mereka ditempatkan di gedung khusus kulit berwarna. Bahkan, ketika Johnson hendak pergi ke toilet pun, ia terpaksa lari sekencang-kencangnya ke gedung khusus itu karena tidak diperbolehkan memakai toilet di dekat ruangan Space Task Group.
Belajar dari konteks film di atas, waktu itu kelompok perempuan kulit hitam ini terancam dibubarkan dan tidak mendapat pekerjaan karena komputer IBM telah mulai digunakan oleh NASA. Ancaman itu begitu nyata sehingga Vaughan mengambil inisiatif untuk mempelajari komputer IBM ini secara diam-diam dan curi-curi. Ia nekad mengambil buku pemrograman dari perpustakaan lokal meskipun harus mendapat hinaan untuk dirinya dan anak-anaknya karena sebenarnya mereka tidak diperbolehkan untuk mengakses perpustakaan tersebut.
Akhirnya, dengan kegigihan yang ia miliki, sekaligus pembelajaran mandiri yang ia upayakan, ia dapat mengajarkan cara memprogram komputer IBM ini kepada kelompok perempuan yang dibawahinya. Kelompok mereka dapat naik posisi menjadi programer dan dapat mempertahankan pekerjaannya. Kalau kita lihat di sini, Vaughan telah melakukan “kecurangan” karena ia dan kawan-kawannya sendiri telah “dicurangi” oleh kaum kulit putih Amerika dengan politik rasisnya. Atas soal yang demikian ini, kita dapat mengajukan pertanyaan kritis: apakah yang disebut kecurangan itu sebenarnya?
Chat GPT, Perspektif Open Source Intelligence, dan Problem Kompleksitas
Berkaca dari bagian sebelumnya, Chat GPT bukanlah suatu hal yang dapat kita pandang buruk begitu saja. Ia dapat menjadi alat bantu pelengkap untuk tugas-tugas kita. Namun demikian, bagaimana hal ini disikapi dengan bijak, itulah yang perlu kita kembangkan sekarang. Dalam batas apa misalnya mahasiswa dapat menggunakannya atau dalam format bagaimana hal ini diintegrasikan dengan pelaksanaan tugas-tugas mahasiswa, itulah yang perlu dipikirkan oleh seorang pendidik pada saat sekarang.
Pada konteks serupa ini, adalah menarik jika melihat Chat GPT sebagai bagian dari Open Source Intelligence. Konsep ini mengajarkan kepada kita bagaimana menggunakan teknologi open source untuk meningkatkan kapasitas kita dalam mencari, menemukan, dan mengolah informasi. Kita menggunakan apa pun yang dapat dijangkau untuk keperluan ini. Contoh yang baik dalam menerapkan konsep ini adalah karya kompilasi yang disusun oleh Aleksandra Bielska, et al., yang berjudul Open Source Intelligence: Tools and Resources Handbook (i-intelligence GmbH, 2018).
Dalam karyanya tersebut, Bielska, et al., menunjukkan bahwa mesin pencari bukanlah sekadar Google atau Bing saja. Untuk alternatif seperti Chat GPT, sebenarnya ada Wolfram Alpha atau Info. Namun demikian, formatnya mendekati Google atau Bing sebagai mesin pencari dan bukannya seperti Chat GPT. Hasil pencariannya relatif bersih dari laman media daring atau laman yang “abal-abal” bila dibandingkan dengan pencarian Google atau Bing. Ini dapat kita gunakan sebagai pelengkap mesin pencari utama. Yang alternatif tidak pernah menjadi sesuatu yang buruk kalau kita mau melihatnya sebagai sesuatu yang potensial dan dapat kita manfaatkan.
Penulis sendiri baru beberapa minggu berinteraksi dengan Chat GPT. Ketika penulis mencoba beberapa aspek yang berkenaan dengan minat riset penulis sendiri, apa yang Chat GPT sampaikan memang masih memiliki limitasinya sendiri. Pertama, Chat GPT dilatih melalui metode in-context-learning dengan 175 miliar parameter (Tom B. Brown, et al., 2005). Ini meliputi pembelajaran in-context-learning dari informasi yang dapat mereka jangkau hingga tahun 2021. Informasi yang bersifat proprietary, seperti informasi dari jurnal ilmiah berbasis indexing ala Scopus/Elsevier, tidak dapat mereka jangkau. Hanya artikel yang bersifat open public yang dapat mereka ambil dan gunakan.
Kedua, pembuatan esai yang di-generate oleh Chat GPT juga sangat bergantung dari instruksi si pengguna. Kalau penggunanya sudah pada level advanced, esai yang dihasilkannya pun akan sangat canggih dan boleh jadi akan dapat digunakan sebagai submission pada artikel jurnal internasional bereputasi. Di dalam kasus yang serupa ini, para dosen, peneliti senior, atau mahasiswa tingkat doktoral pun berpotensi untuk dapat melakukan kecurangannya sendiri. Yang membatasi mereka untuk tidak melakukan hanyalah nurani mereka sendiri dan sikap mereka atas integritas akademik tersebut.
Kedua limitasi tersebut dapat diatasi atau tidaknya sangat bergantung pada usaha Open AI dan penggunanya. Pada limitasi pertama, tentu saja akan ada perlawanan yang cukup besar dari para pembuat indexing jurnal akademik berbasis proprietary jika seandainya Chat GPT menggunakannya dalam pola generate esai yang dibuatnya. Ini akan memungkinkan lahirnya aplikasi pendeteksi esai anti-generating AI yang mungkin akan dibantu oleh AI juga. Perang ini sudah pasti akan dimulai seperti halnya ketika perusahaan tertentu membuat piranti anti-Plagiarisme untuk mendeteksi metode kecurangan copy-paste yang hadir karena munculnya digitalisasi karya ilmiah.
Dalam limitasi kedua, selain kemungkinan kecurangan, inovasi yang terkait dengan karya ilmiah dapat berkembang secara lebih jauh sebenarnya. Hal ini terutama terkait dengan riset-riset multidisiplin atau interdisipliner. Tentu saja paradigma yang dipakai di sini adalah melihat Chat GPT dalam konteks Open Source Intelligence. Upaya serupa ini mungkin sudah dilakukan juga oleh para dosen, peneliti senior, atau mahasiswa doktoral yang cukup kreatif menjadikan Chat GPT sebagai mitra diskusi. Dalam hal ini, tidak ada salahnya menggunakan Chat GPT sebagai salah satu sumber referensi. Namun demikian, hal yang serupa ini juga memiliki kerentanannya sendiri karena screenshot yang dibuat dapat saja dimanipulasi karena Chat GPT tidak memiliki fitur untuk meng-generate percakapannya sebagai laporan/log.
Terlepas dari kerentanan ini, penulis membayangkan bahwa Chat GPT akan menjadi mitra yang cukup mengasyikkan ketika kita dibantu untuk memahami masalah yang kita telaah dalam perspektif ilmu/teknologi yang berbeda dari yang kita kuasai. Misalnya, ketika penulis ingin memahami Kecerdasan Digital yang melibatkan pengukuran psikologis (psikometri), di mana penulis bukan ahli di soal tersebut, input dari Chat GPT ini menjadi sesuatu yang membantu. Selain membaca buku yang berkesesuaian, kita akan mendapat teman untuk menjawab masalah yang kita telaah tanpa kita merasa khawatir akan mengganggu waktu kerja/istirahatnya seperti ketika kita bertanya pada seorang teman sejawat atau seorang Profesor.
Selain itu, dalam fungsinya sebagai alat bantu untuk riset multidisiplin dan interdisiplin, Chat GPT akan dapat memberikan suatu gambaran bagaimana tema yang kita telaah akan dikaji dalam bidang ilmu lainnya. Ini kita butuhkan untuk mendedah masalah yang kompleks semisal yang terdapat dalam SDGs. Misalnya, masalah kemiskinan itu bukanlah masalah sederhana dalam bidang ekonomi. Orang yang mungkin sudah memiliki pendapatan yang cukup besar di atas kategori masyarakat miskin di Indonesia dapat saja memiliki perilaku atau mental sebagai orang miskin. Dalam praktiknya, mereka tidak malu-malu mengaku sebagai orang miskin padahal sudah punya smart tv, motor, atau bahkan mobil untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Mereka akan menggunakan pendekatan terhadap Ketua RT untuk memuluskan maksudnya ini. Ini adalah persoalan karakter “miskin” yang masuk dalam ranah pembahasan psikologi. Ketika misalnya mendapatkan pemahaman atas soal ini dari Chat GPT, meskipun jangan diandaikan akan sangat sempurna masukannya, paling tidak kita akan dapat melihat pada aspek mana keterkaitan masalah yang kompleks ini dalam kaitannya dengan bahasan di bidang lain.
Tentu saja gambaran pemanfaatan Chat GPT ini sebagai alat bantu riset multidisiplin atau interdisiplin dalam mendedah masalah yang kompleks hanya sebuah opsi saja. Ketika kita tidak menyetujuinya karena prinsip tertentu, hal ini juga akan menjadi pilihan lainnya. Ini dikembalikan pada masing-masing individunya. Hanya saja, dalam persoalan ini, apa yang dihadirkan oleh Chat GPT dapat penulis lihat juga dalam sisi sebaliknya, yaitu sebagai pilihan yang cukup prospektif dalam membantu kita menyelesaikan masalah yang kompleks. Kita seharusnya juga sadar bahwa pengetahuan dan database yang kita juga punya terbatas. Kenapa kita tidak berkolaborasi dengan AI untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi ini?
Kota Bogor, 9 Februari 2023