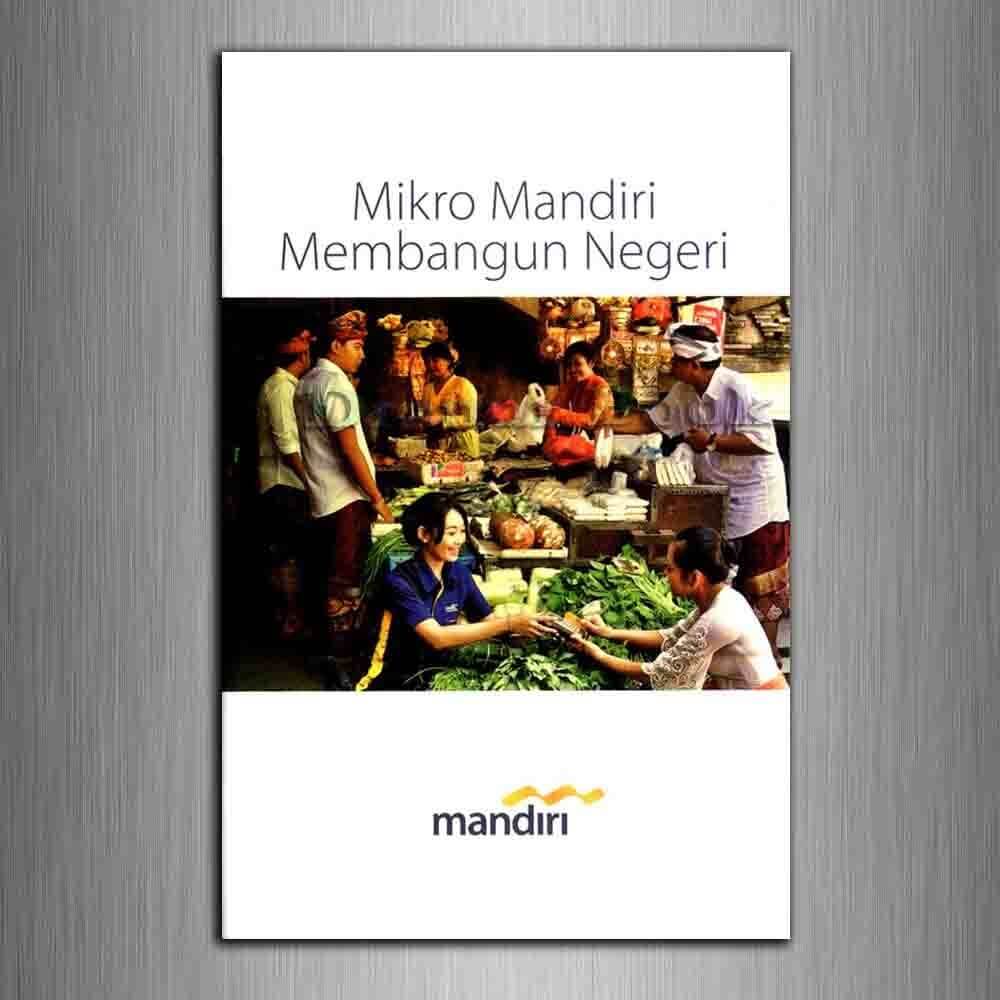Idul Adha sudah 5 hari berlalu. Namun, saya terus diganggu oleh suatu pertanyaan. Ini adalah soal kenapa Ibrahim A.S. diberikan ujian hingga harus “mengorbankan” putranya. Meskipun pada akhirnya diberikan ganti seekor domba untuk putranya itu, saya tetap benar-benar bingung dan bertanya-tanya. Apakah Ibrahim A.S. telah membuat Tuhan-nya marah? Mungkin tidak juga jawabannya seperti ini karena, dalam riwayatnya, Ibrahim A.S. adalah salah satu kekasih Tuhan.
Dalam pemahaman saya yang terbatas, kalau dikaitkan dengan konteks pendidikan, sebuah ujian biasanya diberikan ketika kita akan naik tingkat. Seorang murid akan menjadi mahasiswa setelah ia menyelesaikan dan berhasil lolos dalam ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Saya mengambil contoh ini karena Nadiem sudah menghapus ujian kenaikan tingkat di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kalau sudah diubah pula, mungkin contoh ini menjadi tak relevan artinya. ![]()
Saya jadi berpikir ujian seperti apa yang dibebankan pada saya untuk naik tingkat. Bukannya apa-apa, ini karena saya sudah lulus di batas maksimum pendidikan. Memang ada sih yang namanya pendidikan pasca doktoral, namun ini bukan soal naik tingkat lagi karena lebih fokus pada pemerkayaan pengalaman riset. Atau, jangan-jangan, saya malah salah mengambil contoh dengan mengaitkannya pada soal pendidikan.
Ujian hidup boleh jadi banyak bentuknya. Ada yang diberikan sakit parah hingga ia harus berjuang untuk benar-benar dapat bertahan hidup (semisal penderita kanker). Atau, ada yang ditinggal pergi oleh orang terkasih, entah itu Anak, Kakak, Adik, Suami, Istri, Ayah, Ibu, Kakek, Nenek, Paman, Bibi, atau bahkan Pacar. Atau, ada yang malah diberikan kelebihan hingga ia merasa terkutuk dengan kelebihannya itu (semisal Kurt Cobain dari grup band Nirvana atau Robin William sang komedian). Contoh yang terakhir, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada mereka atas prestasi atau kegeniusan mereka ini, adalah bagian dari paradoks kehidupan.
Boleh jadi, yang lebih tepat konteksnya ketika kita berpikir soal ujian kehidupan adalah berkenaan dengan keterikatan. Ujian hidup diberikan pada kita untuk melepas keterikatan itu sendiri atau mengurai kecanduan terbesar kita. Kita kadang terikat tanpa sadar dengan sesuatu hal. Yang lebih parah adalah ketika kita terikat pada sesuatu yang menyenangkan kita. Ibrahim A.S. mungkin terbuai dengan kehadiran seorang anak yang telah ditunggunya selama 86 tahun. Makanya, Tuhan pun menegurnya dengan cara demikian. Serupa dengan teguran Tuhan atas Muhammad S.A.W. saat mengacuhkan seorang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum dan lebih mementingkan berdakwah pada pembesar Quraisy. “Wahai yang bermuka masam,” Tuhan memanggilnya sedemikian keras dalam Al-Qur’an surat Abasa.
Kalau dalam konteks saya pribadi, ternyata ujian terberat saya ada pada soal buku. Saya baru saja menyadarinya sekarang saat terusik soal pengorbanan. Ia ternyata menjadi lokus keterikatan saya. Hal ini wajar saja karena sedari kecil saya memang lebih banyak ditemani oleh buku. Bahkan, saat diajak pergi oleh Bibi saya untuk ikut ke Blok M, Jakarta, dan ditinggal di toko buku Gramedia karena beliau harus kuliah, saya yang masih berusia 8 tahunan malah senang-senang saja. Buku bagi saya adalah fokus kesenangan.
Pernah satu saat, ketika baru 2 hari keluar dari Rumah Sakit Panti Rapih karena terkena Demam Berdarah di akhir tahun 2002, saya malah memilih untuk diantarkan pergi ke toko buku. Atau, saat dapat THR, ketika orang lain sibuk dengan baju baru atau gadget baru, saya malah lebih terpikir untuk beli buku. Dengan cara ini pula, banyak buku telah datang dalam kehidupan saya. Saya pun lebih dikenal di masa kuliah dengan julukan “perpustakaan berjalan” karena sering bawa buku banyak di ransel. Begitupun di soal penghidupan, saya memilih bekerja sebagai dosen karena terkait dengan kesukaan saya pada buku.
Belakangan ini, dalam kurun waktu 1 bulan, saya dipaksa untuk melepas semua buku penting yang sudah saya kumpulkan bertahun-tahun untuk menyusun buku Sejarah Pemikiran Nusantara. Bukan oleh siapa pun juga, tetapi karena perlu dipaksakan. Sedih dan gak karuan rasanya, tetapi ini sekaligus ujian untuk saya melepas keterikatan. Boleh jadi, saya tidak diminta untuk bersumbangsih di soal ini karena banyak masyarakat Indonesia tidak akan selesai masalahnya dengan hanya satu buku Sejarah Pemikiran Nusantara saja. Mendengarkan keluh kesah saat masyarakat terkena dampak pandemi COVID-19 dalam konteks pendidikan para putra putrinya membuat saya tercekat. Saya diingatkan kembali dengan begitu banyaknya jurang menganga dalam masalah pendidikan yang perlu diselesaikan.
Mungkin inilah yang telah memanggil saya. Ada kewajiban yang lebih besar daripada sekadar menulis satu dua buku atau mengajar di perguruan tinggi. Ini karena saya telah diberikan anugrah besar untuk belajar dan mengenyam pendidikan hingga tingkat tertinggi, yang bagi banyak orang cuma mimpi. Kini waktunya bagi saya untuk mengembalikan apa yang telah saya dapat pada semesta dengan cara berbagi pengetahuan saya kepada sesama dan bekerja dengan format yang tak berbatas. Ini akan saya mulai dengan serius pada laman pribadi saya, sekaligus tempat saya berekspresi untuk apa yang saya pikirkan, rasakan, dan bayangkan. Saya juga ingin menjadi parrhesiast seberani Foucault dan mengukirnya dalam buku kehidupan saya.
Pada akhirnya, buat saya pribadi, pengorbanan adalah melepas semua keterikatan kita pada sesuatu hal. Inilah esensi dari pengorbanan. Pengorbanan itu pun tidak lagi sekadar menyembelih hewan. Apa yang sebenarnya dikorbankan dalam soal ini? Bukankah para hewan itu sendiri yang justru berkurban nyawa untuk kita dan bukan kita yang sedang melakukan pengorbanan? Apa artinya melepas uang 2 hingga 25 juta rupiah jikalau itu tidak melepas keterikatan kita pada sesuatu? Toh, kita semua akan lepas dari dunia ini dan keterikatan pada dunia dengan segala aspeknya akan membawa pada malapetakanya sendiri. Bukankah kita sudah diingatkan bahwa “cinta pada dunia adalah pangkal dari segala keburukan”?
Soal yang terakhir ini, sebenarnya sudah diingatkan cukup lama dengan dongeng Tragedi Raja Midas. Raja Midas memiliki obsesi yang besar atas emas. Ia pada akhirnya diberkati dengan kemampuan untuk menyentuh apa pun menjadi emas. Tak dinyana, kemampuan ini membawa kutukan padanya ketika ia hendak makan ataupun saat memeluk putrinya. Semuanya berubah menjadi emas. Tak dapat pula ia makan dan kehilangan juga putri yang dicintainya. Kisah ini membawa kita pada pelajaran bahwa kekayaan pun tidak akan pernah dapat menghasilkan kebahagiaan. Meski ia akan membawa kesenangan pada awalnya, tetapi hal itu tak akan abadi. Ini akan paralel pelajarannya dengan ibadah kurban. Ketika kurban itu dilaksanakan berkali-kali hanya karena kita memiliki kekayaan yang lebih dari cukup, apakah ini akan membawa kita lepas dari keterikatan pada dunia? Yang tahu jawabannya, mungkin hanya hati kita sendiri.
Depok, 5 Agustus 2020
Unduh artikel/esai ini dalam bentuk pdf