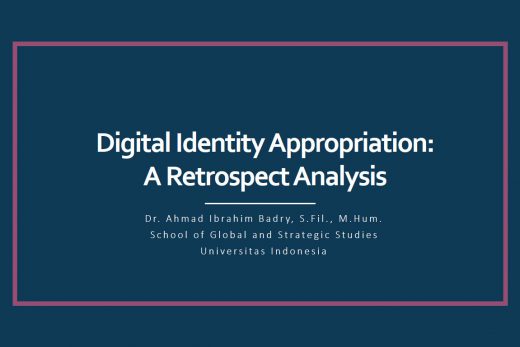Sudah berbulan-bulan, saya tidak bertukar kabar dengan Prof. Riris. Tiba-tiba WA dari beliau masuk pada 24 Juni lalu. Isinya sebuah pesan kalau beliau akan purna tugas dari Universitas Indonesia. Saya membacanya dengan haru mengingat tugas jurnal saya belum terselesaikan dengan baik. Namun, beliau malah lebih banyak bertegur sapa secara pribadi. Inilah momen di mana saya tergerak karena sentuhan kasihnya.
Lama berada dalam ruang yang sama membuat saya terus teringat. Kisah itu adalah perjalanan menyelesaikan studi Doktor di Universitas Indonesia. Beliau adalah Promotor saya bersama Ibu Dr. Karlina Supelli. Mereka berdua adalah Srikandi tangguh dalam dunia pendidikan. Sungguh beruntung, saya dapat bertemu dengan keduanya dalam menjelajah filsafat pada jenjang tertinggi. Yang satu, Prof. Riris, mengajarkan kebernasan dan kesederhanaan untuk menuliskan gagasan, yang lain, Dr. Karlina, mengajarkan kecermatan berpikir dan disiplin waktu.
Sebenarnya, tidak mudah berayun di antara keinginan keduanya. Harus saya akui, filsafat itu ribet, rumit, ruwet, dan banyak berputar. Kadang lebih mudah belajar logika dan programming karena straight to the point. Namun, keindahan filsafat itu ada saat engkau terjun pada kedalamannya secara spiral, melampaui apa yang terlihat dari sekedar mata. Di titik ini, walau setiap orang dapat mencicipinya, seorang doktor filsafat dibebani tugas lain untuk menuangkannya dalam rangkaian cerita bermakna. Tidak dengan cara menemukannya, tetapi hanya merangkainya dengan baik dan benar. Ini karena tidak ada yang tersisa setelah Plato menuliskan semuanya. Filsafat masa kini hanya catatan kakinya Plato, begitu Bertrand Russell berucap. Namun, buat saya, ini adalah mitos lain dari filsafat.
Keluar dari jebakan ayunan itu, hasilnya memang dapat ditulis dengan baik meski jauh dari kata sempurna. Butuh waktu 4,5 tahun untuk menggenapkannya. Saya memang cukup bangga, gembira, dan senang dengan hasilnya, tetapi belum benar-benar puas. Soalnya, kadang terpikir bagaimana merumuskan apa yang saya tulis dalam format yang lebih baik lagi, kadang juga terpikir bagaimana tema yang saya tulis itu dapat membumi di Indonesia yang masih hiruk pikuk dengan urusan politik identitas.
Terlepas dari itu semua, pelajaran terpenting justru saya petik pada prosesnya. Ya, diayun-ayun adalah proses penting yang pernah dijalani kita semua sebenarnya. Saat kita kecil diayun oleh Ibunda/Ayahanda tercinta dalam pelukannya, kita rasakan hal yang paling nyaman hingga tertidur. Namun, rasa nyaman itu menjadi hilang saat kita diayun oleh kehidupan di usia dewasa. Kita lebih suka dengan perhentian atau stabilitas. Ayunan bahkan goyangan kecil saja lebih sering kita hindari. Padahal, hidup kita adalah seni menjalani ayunan itu sendiri, mengikuti iramanya dan mengambil posisi yang terbaik di antara itu semua. Saya tidak suka mengibaratkan hidup seperti roda berputar. Kalau dipikir-pikir lagi, ini analogi yang tidak terlalu pas. Kalau membayangkan saya berada dalam roda berputar, saya yakin akan pusing tujuh keliling. Apalagi, jika ritme putaran rodanya terlalu cepat.
Dalam konteks ini, Prof. Riris sudah berada dalam ayunan yang lambat meskipun belum berhenti. Tiba pada waktu di mana beliau akan menikmati waktu setelah tugas usai bersama keluarga. Selamat memasuki waktu itu Ibu Prof. Riris. Semoga Ibu Prof. Riris mendapatkan kasih yang besar dari semesta karena saya pribadi tetap tidak akan dapat membalas segala kebaikan beliau.
Depok, 28 Juni 2020