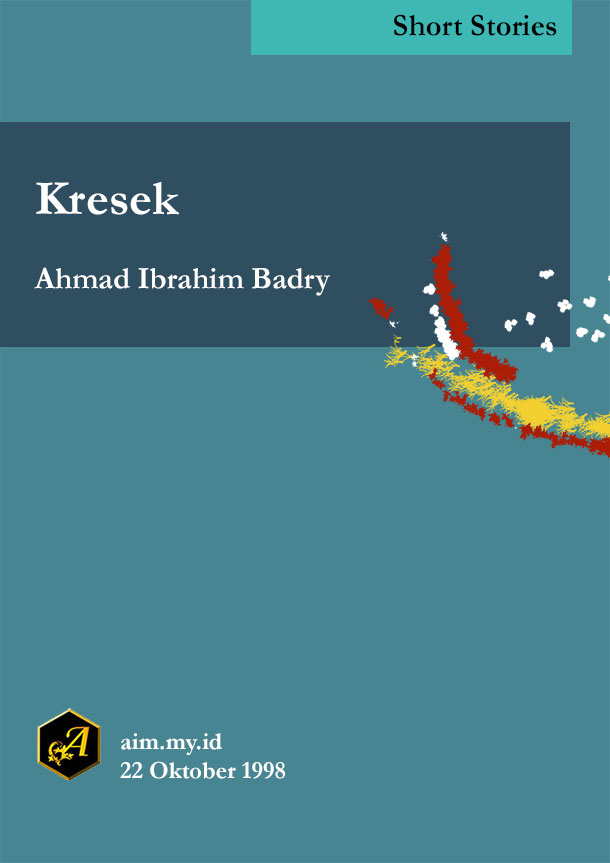saya mungkin tidak pernah menulis sesuatu tentang politik, atau tema yang berbau itu. mungkin, itu karena saya alergi dengan satu wilayah ini. tapi, kali ini, saya terpaksa menulis tentang politik. bukan karena politik itu memang menghasilkan kematian seperti terbersit dalam judul tulisan ini, juga bukan karena saya tertarik untuk masuk dalam wilayah ini. saya menulis justru dengan rasa hormat untuk satu wilayah ini. kenapa demikian?
saya adalah orang yang dibesarkan dalam keluarga politik. sedari kecil, saya sudah bergelut dengan wilayah politik. tempat bermain semasa sekolah dasar pun adalah gedung dpr/mpr yang megah itu. tamu yang datang dan pergi pun lebih banyak yang berkaitan dengan urusan politik. bahkan hingga pemilu 09 april yang lalu, saya selalu harus membuka pintu untuk urusan yang ini. kalau boleh dibilang muak, saya memang udah eneg dari dulu. betapa tidak, 20-an tahun hidup saya ini harus berurusan dengan politik atau mungkin sampai saya mati.
walaupun begitu, saya bukan tipikal orang yang apatis. saya adalah orang yang selalu berusaha untuk mengerti. bahkan untuk sesuatu yang mungkin saya benci. pada politik, saya pun berusaha untuk memahaminya. kenapa wilayah ini selalu dipandang bagai seorang wanita yang seksi atau perempuan yang anggun mempesona?
semakin saya berusaha mendapatkan pengertian, semakin kebingungan itu mengganggu. orang berpolitik adalah orang bermotif. kalau gak pengen ini itu, kadang dia berhasrat untuk suatu pengorbanan. untuk kekuasaan kah? untuk kejayaan kah? untuk ideologi kah? atau untuk sesuatu yang memang tidak dapat saya mengerti?
misalnya, peristiwa politik ketika napoloeon bonaparte menembak jatuh hidung sphinx di gizeh, apa yang ia pikirkan? cemburukah? atau ia merasa tidak berbangga hati dengan perancis karena leluhur mereka tidak meninggalkan monumen sebesar itu?
ribuan pertanyaan atau mungkin jutaan pertanyaan sudah saya lewatkan. semuanya itu tentang politik. termasuk tentang hitler yang harus mendirikan kamp auschwitz untuk melakukan genosida. terlepas dari kontroversi bahwa holocaust itu ada atau tidak ada, tetapi peristiwa politik ini menghasilkan tanda tanya besar bagi saya pribadi.
kalau saya kemudian berpikir tentang batas ambang abnormalitas dalam politik, tolok ukurnya tak pernah jelas. lalu, kenapa kita harus berbicara tentang abnormalitas dalam politik? ya, saya membicarakan hal ini karena politik memang menghasilkan sejenis abnormalitas tertentu. kemarin lawan, besok kawan. kemarin salaman, besok bunuh-bunuhan. ini sejenis abnormalitas yang kalau menggunakan ukuran medis atau psikologis tak bisa diukur.
apakah kriminal ketika ribuan atau jutaan orang indonesia itu dibantai hanya karena mereka masuk organisasi semacam barisan tani indonesia? apakah jahat ketika banyak para kiai disiksa dan dipenjara hanya karena mereka tak mau bernaung di bawah pohon beringin? dalam politik, pertanyaan itu tidak relevan. dogma machiavelli yang mengatakan bahwa politik itu menghalalkan segala cara ternyata menjadi tolok ukur abnormalitas ini. semuanya menjadi normal ketika kita berlaku seperti machiavelli bilang. menjadi abnormal ketika kita berlaku seperti rama mangun yang memegang asas politik hati nurani atau bersikap seperti muhammad natsir yang mengajarkan fatsoen berpolitik.
tingkat abnormalitas pun semakin kacau bila kita kaitkan dengan dua elemen baru dalam politik modern. ada uang dan hawa nafsu. ketika uang menjadi tolok ukur abnormalitas, rasio berpolitik menjadi hilang. politik semata-mata diukur dari segi kelayakan bisnis dan break even point. bila saya mengeluarkan rata-rata rp. 5.000,-/orang untuk 20.000 pemilih atau sebesar seratus juta rupiah, maka saya seharusnya bisa mengambil kembali rp. 50.000,-/orang dari 20.000 pemilih itu atau sebesar satu milyar rupiah.
pada hawa nafsu sebagai pijakan, politik tak ubahnya seperti pramunikmat yang siap memuaskan dahaga si hidung belang. istri pun tak lebih daripada subjek pelengkap penderita. tapi malah ada yang menjadi subjek pelengkap masalah karena minta jatah ratusan juta rupiah per bulan. gaji rp. 30.000.000,-/bln nampaknya sangat jauh dari cukup. walaupun itu setara dengan gaji 6 orang guru bersertifikasi. atau mungkin 3.000 orang guru setingkat sekolah muhammadiyah dalam laskar pelangi.
dengan tingkat abnormalitas serupa itu, saya semakin heran saja kalau ada banyak orang yang mau menjadi caleg. mereka hanya melihat riak air nan tenang pada permukaan dan tidak dapat menduga seberapa dalam pusaran di bawah permukaan itu akan menghisap mereka. korban pun berjatuhan. dari mulai yang stres hingga bunuh diri.
akibat yang terakhir ini adalah resiko terkecil dalam berpolitik. sebab, ada yang lebih beresiko dari itu semua. ya, hilangnya nurani dalam berpolitik adalah resiko terbesar yang harus ditanggung oleh setiap orang yang berkecimpung di dalamnya. tak peduli dia kiai, pendeta, atau filsuf sekalipun. berpolitik adalah bergulat dengan penjagaan nurani yang semakin lama semakin lemah cahayanya.
barangkali ini adalah awal dari kematian kita. kematian sebagai seorang manusia. kita menghindari politik dengan apatis sama dengan membiarkan saudara kita kehilangan nuraninya pelan-pelan. terjun dalam politik pun beresiko kehilangan nurani kita sendiri. tapi saya tidak akan berkata bagai simalakama. karena kita adalah manusia.
saya selalu percaya ada satu cara yang dapat membawa kita dalam perubahan politik yang lebih baik. ya, itu melalui pendidikan politik. lebih tepatnya, pendidikan politik dengan nurani. ada banyak metode yang dapat kita bangun. penguatan pesantren dengan pola pikir kritis, pembelajaran kader politik yang idealis, pembuatan film yang menggugah, atau perluasan jaringan politik kritis. dalam hal ini, saya tidak ingin pesimis seperti halnya adorno atau horkheimer.
kalau dengan kematian saja kita takut, buat apa kita hidup?
Image by Wokandapix from Pixabay