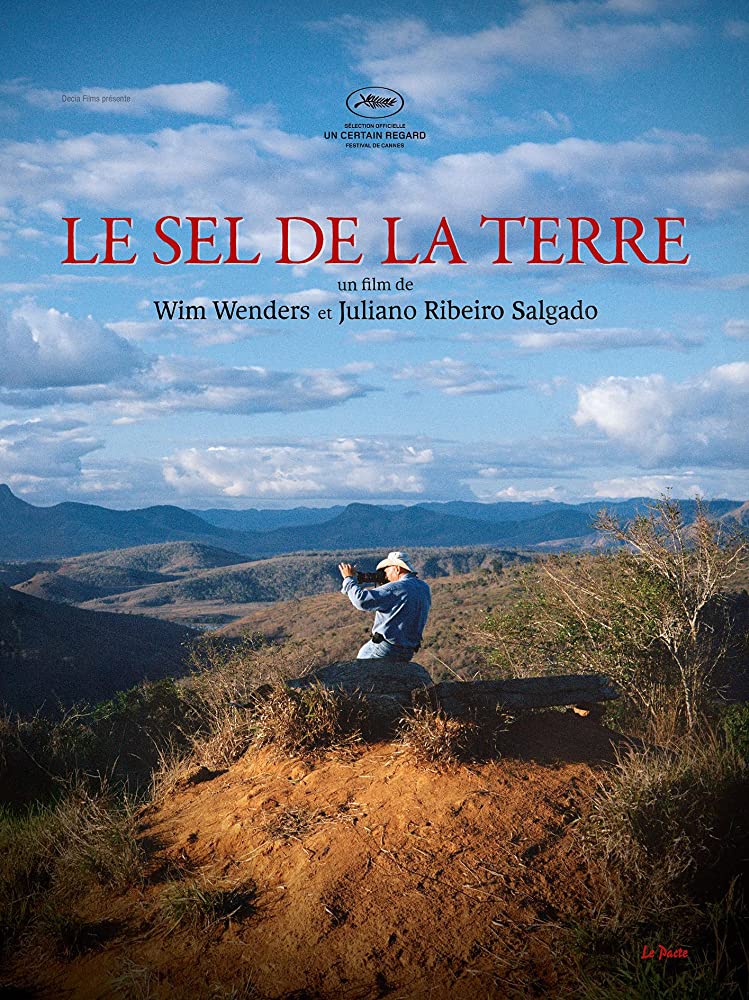Pendahuluan
“Beda pikiran, tentu akan beda dalam perbuatan.”
Awal pembuka dari artikel ini mungkin mengundang tanda tanya? Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini? Apakah ada arti tertentu dalam pernyataan tersebut sehingga dapat dianggap istimewa?
Pernyataan ini sebenarnya merupakan pernyataan yang sederhana. Namun demikian, pernyataan ini mengandaikan hal yang sangat mendasar. Sebab, inilah dasar bagi kita untuk memahami diri kita sendiri sebagai manusia. Pernyataan ini, selain berkaitan dengan identitas, juga berkenaan dengan hal lainnya, terutama dalam hubungan antar individu. Bahwa kita sama sebagai manusia, tetapi akan “berbeda” dalam cara berpikir dan juga dalam tindakan kita.
Penggarisbawahan atas pernyataan ini menjadi sesuatu yang utama dalam apa yang disebut dengan politik perbedaan seperti telah disampaikan dalam artikel yang sebelumnya. Meskipun begitu, pernyataan ini bukan hak milik dari politik perbedaan. Pernyataan ini juga bukan milik dari siapa pun karena ia merupakan konfirmasi dari fakta yang ada dalam hidup seorang manusia. Selain itu, ia mengandaikan pernyataan lain bahwa manusia itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lalu, apa maksud dari semuanya ini?
Kehormatan (Honor), Martabat (Dignity), dan Pengesampingan (Marginalisation)
Oleh karena manusia itu berbeda, hal ini akan mengandaikan satu jenis hubungan antar individu yang tidak sama. Dalam sejarah manusia, manusia dalam hidup berkelompok selalu “ditempatkan” dalam posisi tertentu. Pada masa prasejarah, ada yang hidup sebagai pemburu, ada yang hidup sebagai pengasuh, dan ada yang berperan sebagai pemimpin. Begitu pun ketika manusia masuk dalam zaman perunggu ataupun dalam masa awal revolusi industri, ia hidup dalam posisi yang sudah ditentukan semenjak ia lahir berdasarkan keluarga yang ia miliki.
Ketika ia lahir dalam keluarga kaya, ia akan ditakdirkan untuk dihormati. Namun sebaliknya, bila ia lahir dalam keluarga miskin, ia akan cenderung diabaikan. Kenyataan serupa inilah yang menjadi spirit dari perlawanan kaum romantisisme di Perancis dan juga di Jerman. Jean Jacques Rosseau berbicara tentang pentingnya hubungan dengan sesama. Ini terdapat dalam istilah yang disebutnya sebagai le sentiment de l’existence. Begitu pun Johann Gottlob Herder yang berbicara “Jeder Mensch hat ein eigenes Maass …”, bahwa setiap orang memiliki ukurannya sendiri.[1]
Apa yang disampaikan oleh Rosseau dan Herder tidak lain daripada pernyataan bahwa setiap orang sebenarnya memiliki martabat (dignity), walaupun ia tidak memiliki kehormatan (honor). Argumentasi ini pada masa modern bermuara pada apa yang disebut sebagai liberalisme. Bahwa ada sesuatu kesejajaran yang harus diperjuangkan dan hal ini adalah kesejajaran martabat sesama manusia (equal dignity of human relation). Prinsip ini juga yang menjadi landasan dalam berdemokrasi.
Namun demikian, seperti telah diingatkan oleh Iris Marion Young[2], demokrasi mengandaikan sesuatu yang bermasalah. Ia tidak dapat mengelaborasi hak-hak minoritas. Senada dengan ini, Charles Taylor juga mencatat kelemahan dari paham liberalisme. Ia mengatakan bahwa “…Where the politics of universal dignity fought for forms of nondiscrimination that were quite “blind” to the ways in which citizens differ, …”.[3] Ini menunjukkan bahwa demokrasi ternyata problematik dan justru melakukan suatu bentuk pengesampingan yang lain (marginalization of the others).
Hal ini secara nyata terjadi dalam konteks negara Indonesia. Terutama, jika hal ini berkait dengan etnis minoritas. Di antara etnis minoritas yang selalu berada dalam wilayah pengesampingan ini adalah etnis tionghoa. Padahal, banyak di antara mereka yang “berjasa” untuk Indonesia. Misalnya adalah Susi Susanti, seorang atlit bulutangkis nasional. Ia adalah salah seorang etnis tionghoa yang lahir di Indonesia, berjasa, namun harus mengalami bentuk pengesampingan dengan adanya pertanyaan apakah dia orang Indonesia yang harus dibuktikan oleh selembar kertas atau dokumen kewarganegaraan.
Politik Pengakuan, Politik Perbedaan, dan Liberalisme
Kenyataan yang dialami Susi juga dialami oleh saudara-saudara se-etnisnya. Tetapi, mungkin juga oleh etnis yang lain dengan cara yang berbeda. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar. Kalau dalam demokrasi itu ada bentuk penindasan, maka apakah alternatif jalan keluarnya?
Politik perbedaan, seperti telah disinggung tadi, sebenarnya telah menyediakan satu alternatif. Namun demikian, dalam pandangan Taylor, politik perbedaan juga menyisakan masalah yang sama beratnya seperti terdapat dalam liberalisme. Ia menyebutkan bahwa “… the politics of difference often redefines nondiscrimination as requiring that we make these distinctions the basis of differential treatment.”[4] Differential treatment ini mengandung masalah karena ia justru menghadirkan keistimewaan untuk anggota kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, dalam kasus etnis tionghoa di Indonesia, different treatment yang dimaksud tentunya akan menjadi suatu bentuk perlakuan istimewa bagi etnis tionghoa tersebut.
Hal ini tentu saja tidak dapat diterima mengingat martabat manusia pada hakikatnya sama. Oleh karena itu, jalan keluar yang dikemukakan Taylor terletak pada apa yang disebut sebagai politik pengakuan dan berbasiskan pada nilai penyikapan yang sejajar (equal respect). Lebih jauh, ia mengatakan bahwa “… (b)ut the further demand we are looking at here is that we all recognize the equal value of different cultures; that we not only let them survive, but acknowledge their worth.”[5]
Inilah tawaran Taylor sebagai model alternatif dari politik perbedaan maupun liberalisme yang mengandung masalah. Ia pun menyarankan langkah praktis yang dapat dilakukan untuk merealisasikan gagasan ini melalui bidang pendidikan. Bahwa ada pendidikan nilai budaya yang diberikan kepada individu untuk mengenal dan mengakui budaya lainnya.
Penutup
Inilah yang dapat disampaikan dalam makalah mengenai Politik Pengakuan dalam konteks Multikulturalisme. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi bahan diskusi yang menyenangkan dan juga cukup hangat untuk diperdebatkan. Komentar terakhir untuk hal ini adalah pada pernyataan di atas, “Beda pikiran, tentu akan beda dalam perbuatan” adalah “kenapa tidak?”
Artikel ini disampaikan sebagai bahan diskusi “Menelusuri Basis Teoretis Multikulturalisme – Suatu Kajian Filsafat” yang diselenggarakan oleh Desantara, Jakarta, untuk pertemuan yang keempat.
[1] Dikutip dari Charles Taylor, “Politics of Recognition”, dalam Amy Guttman (Ed.), 1994, Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Princeton University Press, New Jersey, hal. 29-30.
[2] Baca kembali argumentasi Young ini dalam artikel sebelumnya dari penulis yang berjudul Politik Perbedaan sebagai Modus Multikulturalisme (2011).
[3] Taylor, Op.cit., hal. 39.
[4] Taylor, Ibid.
[5] Taylor, Ibid., hal. 64.
Unduh artikel dalam bentuk pdf