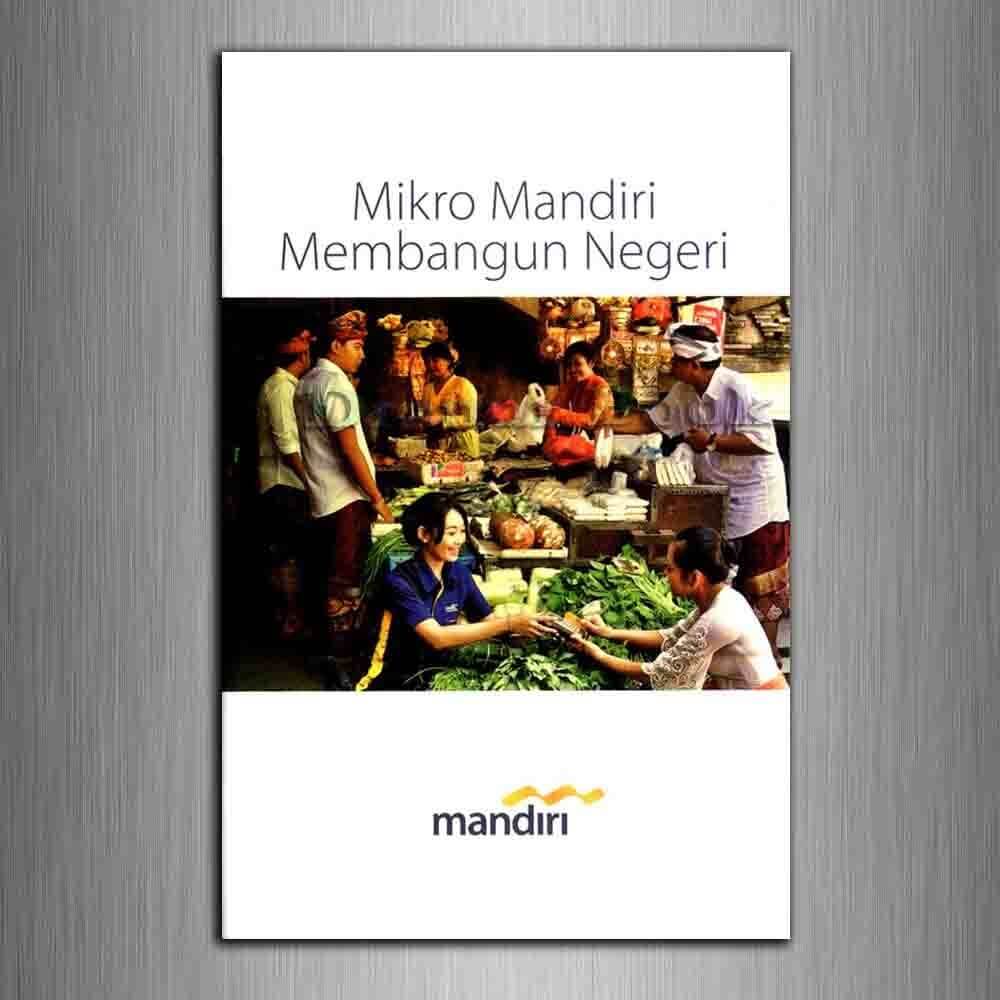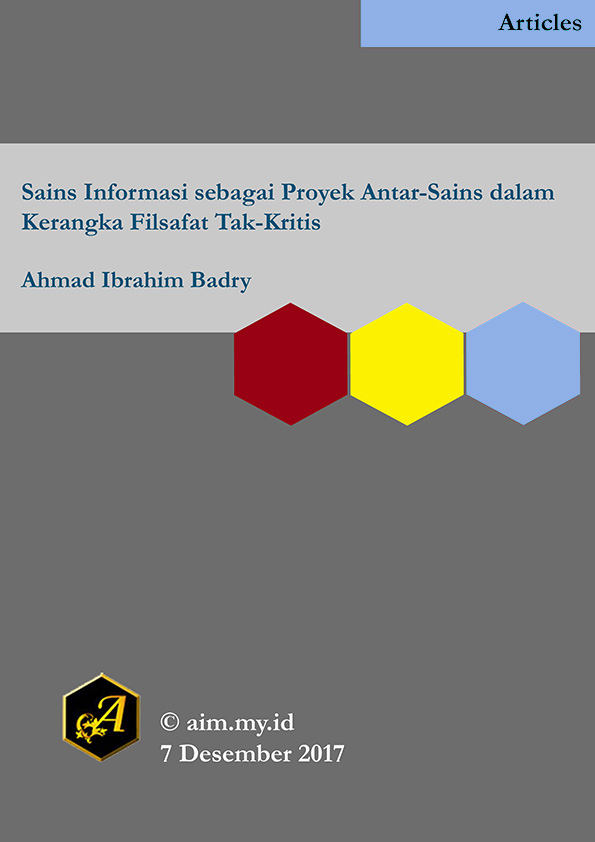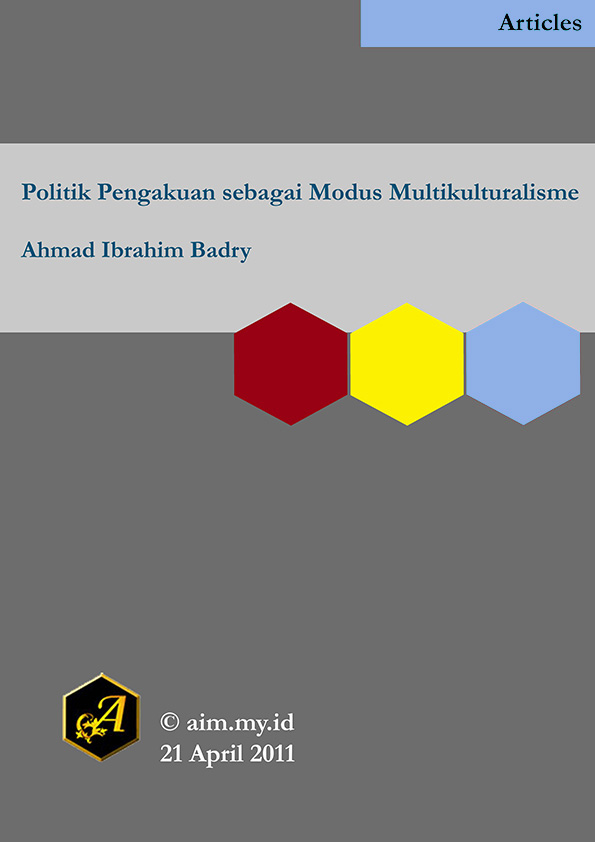I. Desantara sebagai Pintu Masuk
Saya termasuk orang yang tidak mengenal betul siapa sesungguhnya Bisri Effendy (Mas Bisri), yang katanya adalah salah satu aktivis sekaligus etnografer kebudayaan cukup penting untuk masyarakat Adat atau kaum marginal. Ia banyak bergaul dengan mereka ini, berperan sebagai guru, maupun berperan sebagai corong bicara untuk mereka. Meskipun ada banyak tulisannya, saya ternyata tidak tertarik untuk mempelajarinya. Ini karena konsen saya memang bukan di soal ini dan emosi saya belum terlalu intens untuk mendalami soal kebudayaan daerah atau kaum marginal di masa itu.
Boleh jadi, ada jalan takdir kenapa saya bertemu dengan beliau ini, meskipun hanya pada tiga kali kesempatan. Satu saat, saya dihubungi oleh teman yang bernama Ari Ujianto, yang sering dipanggil sebagai Cak Gondes. Ia meminta saya untuk mengisi materi soal Multikulturalisme dalam perspektif filsafat. Waktu itu, di tahun 2011, saya masih dalam proses penyelesaian studi lanjut di Program Magister Filsafat, Universitas Indonesia. Saya sebenarnya bukan ahli di soal ini, tetapi saya coba untuk menyanggupinya sebagai “ban serep” (pembicara dadakan). Ini karena saya juga baru selesai belajar Multikulturalisme dalam mata kuliah yang diasuh Rama Mudji Sutrisno, jadinya ya sekalian saja.
Dari permintaan tersebut, ada empat kali pertemuan yang dirancang. Pertama, saya menyampaikan pembicaraan pengantar soal Multikulturalisme yang dititikberatkan pada pengenalan soal Eropasentrisme. Ini adalah fenomena penjajahan kultural yang dilakukan oleh Eropa pasca Kolonialisme. Kita dijajah melalui jalur peradaban dan kebenaran ilmiah ala Eropa, yang disebarluaskan melalui sekolah modern (silahkan baca di tautan ini untuk penjelasan lengkapnya). Kedua, materi yang disampaikan berkenaan dengan politik identitas sebagai modus Multikulturalisme. Saya membaca melalui yang disampaikan oleh Martin Ramstedt dan Fajar Ibnu Thufail dalam buku suntingan mereka yang berjudul “Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada Masa Pasca-Orde Baru,” (2011, Grasindo), bahwa ada operasionalisasi politik identitas yang tersebar pada ranah politik, agama, dan hukum (ini dapat dibaca seksama pada tautan berikut). Ketiga, materinya berhubungan dengan apa yang disebut sebagai politik perbedaan. Ini adalah soal penyeimbangan antara minoritas dan mayoritas, namun sekaligus menghasilkan dilema dalam prosesnya (bagi yang tertarik dapat membaca di artikel ini). Terakhir, saya menyajikan ulasan sederhana atas soal politik pengakuan. Ini dirumuskan oleh Charles Taylor sebagai suatu penyikapan yang sejajar (equal respect) atas kelompok marginal/minoritas (silahkan ditelusuri lebih jauh di tulisan berikut). Inilah yang saya coba identifikasi dan rangkum dalam perbincangan dalam Multikulturalisme.
Setelah penyampaian materi ini, saya pun menjadi lebih intens kontak dengan Desantara. Ini adalah lembaga yang didirikan oleh Mas Bisri beserta teman-temannya. Tentu saja, apa yang diusahakan Desantara dalam soal kebudayaan jauh lebih besar daripada sekedar diskusi Multikulturalisme yang saya paparkan. Ini seperti buih dalam lautan. Anda dapat membuktikannya kalau Anda melakukan riset pada arsip-arsip Desantara, dari mulai majalah Desantara, jurnal Srinthil, hingga buku-buku terbitannya. Namun, di saat saya masuk ke lembaga ini, apa yang sudah diusahakan dan tertuang dalam banyak diskusi dan laporan penelitian, hasilnya tidak terakselerasi dengan baik. Dalam maksud revitalisasi organisasi Desantara inilah saya pertama kali bertemu dengan Mas Bisri.
Waktu itu, di tahun 2012, saya berkunjung ke rumah beliau bersama Ari Ujianto dan Adee Dwi Setyaningsih. Kami seperti berziarah menelusuri sesepuh Desantara untuk mencari elan vital organisasi Desantara yang hilang. Pada kesempatan tersebut, beliau menyambut hangat dalam bincang yang akrab. Tampak dalam perbincangan itu, beliau sangat menguasai soal kebudayaan dengan baik. Kalau saya tidak salah ingat, beliau menekankan pentingnya berjejaring. “Desantara harus kembali menaut silaturahmi dengan jaringan masyarakat Adat dan kaum marginal. Desantara itu besar karena karakter berjejaringnya yang kuat,” begitu kira-kira wejangan beliau.
Selang beberapa lama, saya diundang dalam salah satu kegiatan Desantara yang mendiskusikan soal Ekologi dan Pembangunan. Pembicaranya adalah Mas Bisri. Dalam diskusi ini, hadir pula Hikmat Budiman, Muhammad Nur Khoiron, dan rekan Desantara yang lainnya. Sayangnya, saya datang terlambat. Namun, dalam perbincangan itu, ada sesuatu yang terngiang hingga sekarang. Beliau bilang, “Kenapa sih pembangunan itu selalu menekankan pembuatan infrastruktur jalan tol dan bukannya memprioritaskan pembangunan transportasi publik yang baik? Saya jadi curiga kalau Negara itu sebenarnya berusaha untuk membuat masyarakat tidak berkerumun. Ini karena kerumunan massa dapat membahayakan posisi kekuasaan.” Mungkin redaksinya tidak tepat betul seperti ini karena hanya berdasarkan ingatan. Namun, ini adalah lontaran penting dan kritis soal bagaimana pembangunan infrastruktur ditafsirkan dalam konteks bersosial dan berkebudayaan. Buat saya pribadi yang bergelut dalam soal filsafat teknologi, hal serupa ini boleh dikata seperti oase sekaligus enigma dalam perluasan perspektif.
Yang terakhir, saya bertemu dengannya saat diskusi internal Desantara. Ada beberapa masukan yang mendasar untuk pengembangan organisasi dari beliau. Ini berkaitan dengan isu keperempuanan. Beliau menyoroti kalau Desantara pada tahun 2013 tidak mengupdate isu di soal perempuan. Ini karena Desantara juga dikenal dengan baik sebelumnya karena diskursus keperempuanan dalam konteks budaya, melengkapi apa yang pernah dilontarkan oleh Jurnal Perempuan yang diusung oleh Gadis Arivia beserta para sahabatnya.
Inilah yang masih saya ingat dari berinteraksi dengan beliau. Meskipun redaksinya tidak sepenuhnya sama, rekam jejaknya masih membayang dengan begitu kuat.
II. Pelajaran Saya dari Kerumunan Massa dan Mas Bisri
Sedari kecil, saya mungkin tidak terbiasa dengan kerumunan karena tinggal di perumahan. Hanya ada beberapa teman yang dapat akrab dengan saya, pun di sekolah juga begitu. Ini karena saya mungkin tidak suka dipanggil dengan “helm,” semasa SD di Jakarta, untuk mengejek rambut poni saya yang lurus. Padahal, tukang cukur membuatnya seperti itu karena permintaan dari Bapak ketika datang ke sana adalah cuma “rapi”. Waktu itu, karena film dari Adi Bing Slamet yang rambutnya lurus dan berponi sedang hits, boleh jadi tukang cukur pun menjadikannya sebagai referensi karena kemiripan jenis rambut saya. Kalau dipotong terlalu pendek ala tentara, potongan rambut saya kurang bagus karena ia akan sedikit mengarah ke atas. “Jocong,” kalau orang Sunda bilang, yang artinya keras kayak batang padi.
Pengalaman ini membuat saya tidak mudah mengakrabi orang di luar sanak saudara. Bahkan, ketika akhirnya saya harus pindah ke Singaparna saat Bapak sudah pensiun, saya sangat malu dilihat hampir seluruh anak SD di tempat saya pindah. Walaupun akhirnya saya tahu masalahnya bukan ada di fisik saya, tetapi karena koper President yang saya pakai, saya jadi merasa aneh sendiri. Bagi mereka yang ada di daerah, tas koper President hanya ada di TV dan tak terjangkau. Sehingga, ketika saya membawanya ke sekolah, mereka mungkin saja kaget karena ada anak yang punya tas itu.
Belakangan, teman-teman di SD baru ini dapat menjadi akrab karena saya sering ikut main sepak bola bersama mereka saat istirahat. Tak pernah sekalipun teman-teman ini memanggil saya dengan cara teman sekolah yang ada di Jakarta. Mereka pun mau main dan datang ke rumah meskipun agak jauh dari sekolah. Namun demikian, perasaaan asing itu tidak pernah hilang hingga saya berada di kuliah.
Sekolah adalah tempat berkerumunnya orang dan itu satu-satunya kerumunan yang dapat saya masuki dengan baik. Ini akan berbeda dengan kampung/desa, yang tingkat kerumunannya sangat intens. Orang satu kampung/desa dapat mengenal seluruh orang dari kampungnya, termasuk putra/putri siapanya. Pengalaman ini tidak pernah saya dapatkan hingga saya berada di Singaparna. Saya kaget juga ketika berbelanja di pasar masih ada orang yang dapat mengenali saya karena wajah saya yang mirip dengan Ibu.
Dengan cara ini, saya menjadi berjarak dengan kerumunan, apalagi dengan kerumunan massa ala supporter bola atau penikmat konser musik. Kebisingan yang tidak saya sukai menjadi salah satu faktor kenapa saya enggan berkerumun di dua event ini. Perubahan mendasar baru saya rasakan saat kuliah ketika saya berorganisasi. Di sini, saya menjadi lebih cair dan akrab dalam kerumunan. Namun, tetap saja, pengalaman ini tidak dapat melepaskan jarak yang ada di antara saya dan kerumunan.
Jarak ini pun semakin terlebarkan saat peristiwa politik menjelang. Ini karena saya melihat kerumunan dapat membuat orang brutal dan sekaligus memisahkan persaudaraan. Ini terjadi saat peristiwa Mei 1998 ketika saudara sebangsa kita yang berasal dari etnis Tionghoa menjadi korban kerumunan massa (baca rangkaian kronologisnya di Historia.id). Di luar peristiwa politik, adapula kekejian kerumunan massa di sana. Misalnya, saat seorang yang diduga sebagai pencuri amplifier di mushala daerah Bekasi pada 1 Agustus 2017 dihabisi dengan cara dibakar hidup-hidup karena amarahnya massa (lihat di Tempo.co).
Apa yang saya alami, rasakan, dan lihat, sebenarnya, merupakan tesis yang berkebalikan dari apa yang disampaikan oleh Mas Bisri. Namun, ketika saya mencoba memahaminya lebih jauh, boleh jadi Mas Bisri memaksudkannya lain. Ia justru ingin melihat aspek positif dari berkerumun, yaitu pada bagaimana kita dapat membuka diri dan percaya pada yang lain. Ini yang saya juga rasakan saat naik kereta ekonomi untuk berangkat dari rumah atau mudik semasa kuliah di Yogyakarta. Banyak kali orang mengakrabi saya dengan ramah, terutama ketika mereka sesama mahasiswa atau orangtua sepuh.
Peristiwa 1998 juga bukan sekadar kesedihan bagi saudara kita dari Etnis Tionghoa, tetapi juga menyimpan potensi perubahan besar bagi bangsa Indonesia dengan adanya reformasi karena kerumunan mahasiswa. Kerumunan massa pun dapat menjadi sangat solider ketika ada tetangga yang meninggal. Masalahnya, dalam soal kerumunan massa, hal ini menjadi buruk ketika mereka tidak sabar dan tak mau memberi ruang untuk mengenal yang berbeda, yang minor, dan yang lain.
Sekat positif dari kerumunan massa inilah yang menjadi sorotan dan coba dibuka oleh Mas Bisri lewat kritiknya itu. Saya pun dapat terjerumus pada kesalahan ketika memahami beliau ini kalau saya juga tidak membuka celah tersebut. Saya memang tidak punya kesempatan untuk mengkofirmasi soal ini dan menimba sumur lebih dalam lagi karena beliau sudah menjadi sepenuhnya terbuka pada alam lain di 17 Agustus lalu, tapi inilah warisan kecilnya pada saya. Sugeng tindhak Mas Bisri! Dalem pun ngertos “renggangan”-ipun.
Depok, 27 Agustus 2020