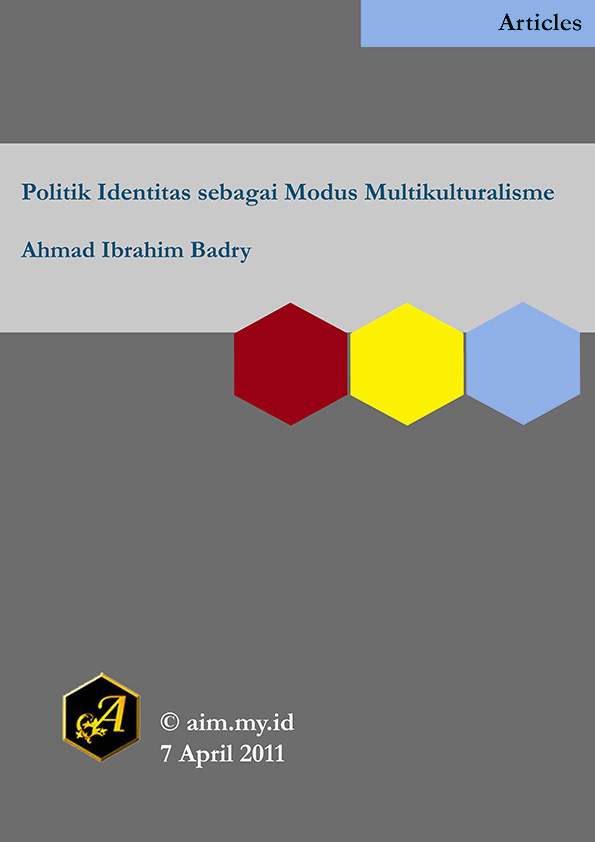Bungkus Koran Lusuh hingga Buku Leces berisi Kode Program
Waktu itu, di sekitaran tahun 1991, saya menerima titipan untuk Ibu saya dari seseorang. Saya lupa isinya apa, tetapi bungkusnya yang terasa istimewa. Sepintas, ini seperti koran lusuh yang biasa dipakai untuk mengirim sesuatu. Kalau di Singaparna, koran dipakai untuk membungkus makanan kering sejenis rangginang yang belum matang, atau oleh-oleh Hajian dengan pernak-pernik minimal seperti kurma, air zamzam, dan kacang arab. Namun, kali itu, saya sepertinya terpikat dengan gambar halaman depannya. Penuh warna-warni dan ini koran yang lain dari biasa. Ada judul Komputek dengan huruf besar yang mencolok. Tak lama setelah menyimpan barangnya, saya coba baca-baca isinya. Saya bengong tidak mengerti. Ini isinya apaan sih ya? Di halaman awal, ada juga banyak baris berulang berisi kode yang ditulis dalam BASIC. Walaupun tidak paham, akhirnya saya simpan koran itu rapi dalam koper President saya, tas sekolah semasa SD.
Selang beberapa lama, saya diajak orangtua pergi ke kota Tasikmalaya. Waktu itu, mobil Colt-nya Bapak diparkir di jalan KH. Zaenal Mustofa. Letaknya tidak jauh dari toko buku Cerdas dan lebih dekat ke toko bahan kain, kalau saya tidak salah ingat. Saya tidak ikut pergi tetapi menunggu di dalam mobil. Tiba-tiba, saya ingin keluar dan melihat-lihat di lapak majalah yang ada di depan mobil. Saya bingung mau beli apa. Saat melihat majalah Infokomputer dengan gambar Virus di depannya yang diilustrasikan dengan monster memanjat tabung monitor, saya pikir cocok untuk dibeli nih. “Lumayan juga ada stikernya,” kata saya dalam hati. Harganya sekira Rp. 1.500,- (kalau tidak salah ingat) atau sepadan dengan uang jajan berikut ongkos selama 5 hari. Kebetulan, waktu itu saya lagi punya uang makanya berani datang ke lapak. Ini agak berbeda dengan yang biasanya saya beli, seperti komik Tiger Wong/ Tapak Sakti atau cerita silat Wiro Sableng/ Pendekar Rajawali Sakti. Saya biasanya harus menyisihkan uang untuk membelinya dengan tanpa jajan selama 1-2 minggu. Risikonya adalah jalan kaki sejauh 2 km dari rumah kalau berangkat dan pulang ke sekolah.
Dari pembelian pertama majalah Infokomputer, saya keranjingan dengan majalah. Selain Infokomputer, saya juga tertarik dengan majalah Trubus dan Aku Tahu. Yang pertama berisi informasi seputar pertanian dan peternakan, yang kedua berisi informasi seputar sains dan teknologi. Walaupun masih gagal paham dengan isi dari majalah Infokomputer yang berkaitan dengan baris kode, saya tetap berusaha membacanya. Dalam peribahasa Sunda, saya ini seperti “monyet ngagugulung kalapa” (monyet mencoba buka kelapa). Ketika berada di kelas 2 SMA, saya membeli majalah Infokomputer lama terbitan 1982. Ini karena saya tertarik dengan baris kode yang dapat memunculkan grafik. Kodenya ditulis dalam BASIC dan kalau kita memasukkan persamaan matematika tertentu, semisal persamaan kuadrat, maka di layar akan muncul grafiknya. Saya merasa beruntung membeli majalah itu dan ingin mencobanya. Sayang, saya tidak punya komputer karena harganya masih terlalu mahal sebanding dengan 1 atau 2 motor semasa itu.
Suatu hari, setelah lama berselang, saya diajak ke rumah teman yang bernama Budi Haeruman bersama Irwandi. Saya lupa ceritanya kenapa saya diajak ke sana. Entah karena cerita soal majalah yang terakhir disebutkan, entah karena kebetulan. Yang jelas, saya jadi heran sendiri kenapa majalah itu juga dibawa. Saat sampai di rumahnya, kami ngobrol cukup asyik. Ternyata di kamarnya Budi ada komputer dengan spek lumayan karena sudah dapat menjalankan Windows 95. Setelah menceritakan soal program yang ada di majalah, saya minta izin untuk mencobanya di komputer itu. Untungnya, di komputer itu ada program BASIC yang menjadi bawaan Windows 95. Jadinya, setelah program selesai ditulis dan dijalankan, di layar komputer muncul menu untuk memasukkan persamaan dan nilai yang hendak dihitung. Input persamaan dan nilai pun diberikan dan, voila, grafik itu muncul. It is like a magic for me. Kami sangat senang dan antusias karena programnya jalan. Budi dan Irwandi pun sama-sama coba masukkan persamaan dan nilai untuk melihat hasilnya. Tak dinyana, saya dapat mempraktikkan program itu secara nyata meski tak punya komputer.
Keberhasilan itu membuat saya semangat. Ada kejadian-kejadian menarik yang masih terasa membekas. Saya jadi belajar kode program secara otodidak dengan membeli buku komputer atau majalah Mikrodata, memfotokopi buku matematika Linear Programming milik Bibi yang kuliah di Informatika dan sering naruh saya di Gramedia Blok M semasa kecil, serta memberanikan diri datang sendirian ke rental komputer di daerah Kudang, Singaparna, dengan modal membeli disket floppy 5 ¼ dan 3 ½ inch. Namun, saya gagal mempraktikkan penulisan program BASIC secara mandiri karena di rental itu tidak ada program BASIC dalam sistem operasi DOS yang digunakan. DOS yang saya kopikan ke disket floppy juga tidak ada program BASIC-nya. Kegagalan ini tidak membuat saya takut saat memberanikan diri maju ke depan sebagai volunteer untuk mencoba program BASIC yang gagal ditunjukkan keberhasilannya oleh guru Matematika kami. Saya ternyata juga gagal. [ Padahal, udah gaya biar kelihatan pinter. 😀 ] Yang lebih tidak tanggung lagi, di lain waktu, saya beranikan diri untuk membeli buku Matematika Kombinatorik terbitan UI di toko buku pada Supermarket yang ada di Jl. Gunung Pereng, Kota Tasikmalaya (yang saya tahu sekarang jadi Matahari Mall). Padahal, harga bukunya itu Rp. 15.000,- dan itu uang yang tersisa untuk ongkos pulang sehabis ikut Bimbingan Belajar UMPTN di Primagama. Untungnya, orangtua saya jadi datang ke dokter gigi yang ada di Jl. Mayor Utarya. Jadinya, saya tidak perlu jalan kaki dari Kota Tasikmalaya ke Singaparna sejauh 12 km-an, meskipun tadinya sudah siap juga sih. [ 😛 ]
Dari pengalaman itu dan karena keluguan, saya pun coba menulis kode program yang saya bayangkan akan jadi sistem operasi pengganti Windows 95 dalam sebuah buku leces. Semangatnya membara khas anak muda. Saya lupa berapa baris kode yang sudah dituliskan. Namun, saya terus mencoba dan membayangkan seperti apa alurnya meski tidak tuntas. Buku leces-nya ini masih tersimpan rapi di rumah Ibu saya di Singaparna bersama dengan kertas koran Komputek lusuh, majalah Infokomputer, dan buku/majalah yang saya beli saat dari SMP hingga SMA. Inilah jejak-jejak awal saya belajar komputer dan pemprograman.
Pergulatan Setengah Gila karena “Virtual Reality”
Di pertengahan kelas 3 SMA, saya jadi tertarik dan berencana untuk mengambil jurusan Matematika. Oleh karena itu, waktu Ibu pergi ke Bandung, saya titip dibelikan buku Matematika. Ketika beliau datang kembali, dua buku Matematika yang berjudul “Kalkulus dan Geometri Analitik” serta “Aljabar Linier Elementer” pun didapat. Ada tambahan bonus kamus Bahasa Inggris dari John Echols dan Hassan Sadily. Saya senang bukan kepalang dan jadi tahu kalau ada buku-buku teks yang bagus. Saat berkesempatan ke Bandung, saya pun mampir di Pasar Suci, untuk beli buku Fisika karya Resnick, setelah dapat info dari kakak sepupu saya, Heri Purnama, yang waktu itu sedang studi di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran (UNPAD).
Ketika akhirnya lulus dari SMA, rencana saya untuk mengambil jurusan Matematika tidak berjalan mulus karena orangtua tidak terlalu merespon. Waktu itu, konsentrasi Ibu saya adalah mengurus Bapak yang sakit keras dan itu juga yang membuat saya tak dapat ikut study tour ke Yogyakarta bersama teman-teman SMA. Saat seminggu sebelum UMPTN (sekarang dikenal SPMB), saya pamit kepada Ibu untuk pergi ke Bandung untuk mengikuti ujiannya dan juga tes masuk di STT Telkom. “Pamit sama Bapak dulu sana,” Ibu bilang sama saya karena Bapak sedang dirawat di Tasikmalaya. Saya agak enggan karena telah berencana ke Bandung bersama teman-teman lewat jalur Garut. Ini agak merepotkan kalau harus ke Tasikmalaya dulu karena jalannya yang memutar. Akhirnya, saya bilang ke Ibu untuk menyampaikan salam pamit ke Bapak dan akan menjenguk Bapak sehabis pulang dari Bandung.
Kami lalu berangkat ke Bandung. Ada Cucu Abdul Nasir dan beberapa teman lainnya. [ Ini agak lupa dengan siapa-siapanya. 🙂 ] Sesampainya di Bandung, kami sempat mampir di rumahnya Tedi Susilo di Margahayu Raya lalu melanjutkan perjalanan ke kos sepupu saya, Heri Purnama, yang terletak di Dipati Ukur. Agak apes karena di kosnya kosong dan baru bisa ketemu setelah menunggu berjam-jam karena dia mungkin ada kegiatan sampai malam hari. Berselang berapa hari, di Sabtu tanggal 17 Juni 1995, saya mengikuti tes masuk STT Telkom. Di sana, saya bertemu dengan teman satu SD yang bernama Muhammad Arif.
Di hari Minggu, saya istirahat sembari membaca-baca kembali soal UMPTN karena dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa yang akan datang. Tiba-tiba, di sore hari, ada saudara yang bernama Mang Asep datang, begitu juga dengan kakak sepupu lainnya, Cecep Abdul Qayum. Mereka bilang Bapak mau segera bertemu. Sehabis maghrib, kami bergegas ke Kota Tasikmalaya. Sesampainya di rumah Bapak yang ada di Gunung Pongpok, saya agak terkejut karena ada banyak orang berkumpul. Ternyata, Bapak sudah tiada. Saya tidak dapat berkata-kata, selain bergegas ambil air wudhu setelah dipeluk oleh Ibu dan saudara-saudara lain. Saya buka kain kafan di bagian wajah untuk melihatnya terakhir kali lalu menshalatkannya. Ini kehilangan kedua untuk Ibu yang menyesakkan beliau setelah dua bulan sebelumnya Nenek dari Ibu juga wafat. Bagi saya, ini suatu rasa sesal kenapa saya tidak mendengarkan kata Ibu. Kelak, rasa ini jugalah yang melandasi saya kembali mengabdi dalam pekerjaan di Tasikmalaya selepas kuliah.
Saya tidak dapat berlama-lama larut dalam kesedihan karena ujian UMPTN sudah menjelang. Senin sore saya sudah kembali ke Bandung diantar oleh Mang Asep. Dengan perasaan melayang, saya mencoba jawab semua soal dengan baik. Sembari menunggu UMPTN diumumkan, saya mencari alternatif lain untuk kuliah. Ada Politeknik ITB di Ciwaruga yang menjadi incaran saya. Namun, nasib ternyata membawa saya masuk ke UGM. Padahal, jurusan Filsafat adalah pilihan terakhir yang iseng karena tidak tahu harus mengisi jurusan apa untuk bidang sosial dalam kategori IPC di UMPTN. Pilihannya adalah Teknik Fisika ITB, Teknologi Hasil Pertanian UNPAD, dan Filsafat UGM.
Singkat cerita, saya pun tekejut-kejut saat masuk kuliah di Filsafat. Ada banyak istilah bahasa asing berseliweran, mulai dari bahasa Inggris, Latin, Perancis, Jerman, India, Tiongkok, Arab, hingga Jawa. Beberapa dosen malah menyampaikan kuliah dalam campuran dengan bahasa Jawa pula. Busyet deh, di semester I, saya setengah mati memahami ini semua. Mendengarkan teman mendiskusikan konsep sekularisme yang berasal dari gagasan Nurcholish Madjid membuat saya kembali bengong. Ini apa sih maksudnya. Akhirnya, karakter saya untuk otodidak muncul lagi. Saya jadi rajin ke Perpustakaan, meminjam buku ini dan itu. Adakalanya dibaca, adakalanya cuma saya bawa di tas sambil jalan-jalan. Bagi saya, yang penting adalah mengakrabi bukunya, serupa dengan masa di SMP/SMA. Selain itu, saya jadi rajin mendengarkan diskusi dan mulai membeli buku di luar buku kuliah. Atas kebutuhan itu dan karena saya harus berhemat sekali untuk biaya hidup, saya niatkan puasa berselang sehari atau puasa Daud hingga berlanjut sampai dua tahun.
Namun demikian, yang paling membekas dalam pencarian referensi, saya tetap terobsesi dengan Matematika. Saya cari referensi Matematika/Filsafat Matematika sekaligus. Belakangan, saya dapat suatu referensi yang menjelaskan konsep Matematika tiga dimensi (3D) yang disebut Segitiga Bola. Penjelasannya membuat saya teringat akan pertanyaan saya semasa SMA pada guru Matematika saya. Waktu itu, pelajarannya terkait dengan cara menghitung jarak antar titik menggunakan konsep Lintang dan Bujur pada peta bumi. Soal yang selalu diberikan adalah garis lurus di antara Lintang Utara dan Lintang Selatan atau Bujur Barat dan Bujur Timur. Saya akhirnya bertanya pada guru saya itu, “Pak, kalau caranya menghitung garis diagonal atau garis yang Lintang dan Bujur-nya beda itu gimana?” Guru saya tak dapat menjawab pertanyaan itu karena ternyata perhitungannya harus menggunakan konsep Segitiga Bola ini. Kalau sekarang, ini mudah sekali dijawab menggunakan aplikasi Google Maps. Tinggal mengisikan nama kota yang hendak dituju dan kota asal pada menu Direction yang ada Google Maps. Voila, jarak beserta peta jalur jalan yang dituju muncul dengan detil. Bahkan, melihat jalan hingga bangunan yang ada di sepanjang jalan itu pun begitu mudah dilakukan dengan aplikasi Google Street. Ini sudah mirip dengan Virtual Reality (VR) yang dulu saya baca pada tabloid Komputek edisi khusus VR di tahun 1994. Bahwa kita dapat menjelajahi dunia tanpa harus pergi dari tempat kita tinggal.
Hingga tiba di semester akhir perkuliahan Fakultas Filsafat UGM, saya masih menggadang-gadang, materi apa yang perlu saya kaji dalam penulisan skripsi. Waktu itu, saya tertarik untuk menulis pemikiran Ludwig Wittgenstein atau kajian khusus mengenai Logika yang akan menelaah Pola Pertautan di antara Proposisi Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, dan Logis. Namun demikian, kedua materi ini urung dijadikan bahan skripsi karena saat berjalan-jalan ke IKIP Yogya (sekarang UNY), saya malah menemukan buku Cyberspace for Beginners (terbitan Mizan) di lapak buku bekas. Saya langsung membelinya, selain karena murah, juga menarik minat saya yang memang tidak asing dengan materi-materi sekitar dunia Teknologi Informasi (TI). Buku itu menyeret saya kembali ke ingatan soal-soal yang sempat terlupakan tetapi intens saya pelajari hingga SMA.
Dengan mantap, akhirnya saya memutuskan untuk mengangkat tema dunia siber dalam skripsi saya. Oleh karena saya juga sedang tertarik dengan pendekatan semiotika, yang dikenalkan pada saya oleh kakak kelas yang bernama Antariksa, saya putuskan untuk menggunakan pendekatan tersebut dalam kajian atas dunia siber. Ternyata, meskipun berhasil dalam ujian proposalnya, tak dinyana saya mengalami kesulitan luar biasa untuk menyelesaikan tema kajian tersebut. Hambatan pertama muncul dari kurangnya referensi yang membahas soal tersebut karena referensi yang dibutuhkan saya memang baru bermunculan bersamaan dengan waktu saya mengambil tema ini sebagai bahan penulisan skripsi. Itupun muncul dan diterbitkan di Inggris. Misalnya saja, buku dari Peter Bøgh Andersen yang berjudul A Theory of Computer Semiotics baru terbit di 1997, atau 2 tahun lebih awal dari saat saya mengajukan proposal dan baru saya dapatkan di kisaran tahun 2000-an atas bantuan teman saya yang bernama Muhammad Radius Anwar. Hambatan kedua terjadi karena saya bingung menentukan pokok-pokok kajian apa saja yang berkenaan dengan materi dunia siber karena sangat luas dari yang saya perkirakan. Hal ini karena buku panduan kajian di soal ini bahkan belum ada (lebih tepatnya, belum terjangkau/diakses oleh saya). Selain itu, tiadanya teman diskusi yang mengenal kedua aspek (dunia siber dan semiotika) penting dalam tema penulisan saya, menjadikan saya sebagai pejalan mandiri di soal ini. Meskipun begitu, saya masih beruntung karena dapat berkenalan dengan seorang yang bernama Ganjar Nugroho, yang cukup membantu saya memahami penerapan semiotika pada bidang sosial. Sementara itu, untuk bidang TI, kebetulan juga teman sekos saya, Nadhif Alawi, ada yang kuliah di Teknik Elektro dan sedang menggeluti juga bidang TI dalam skripsinya dengan tema Pembelajaran melalui VR. Jadinya, saya merasa klop berdiskusi dengan kedua orang ini.
Dengan semua hambatan ini, saya mengerjakan skripsi dengan satu prinsip yang diajarkan oleh salah seorang pembimbing saya, bapak Farid Mustofa, yaitu berusaha menulis 1 halaman setiap harinya. Tahun demi tahun saya bekerja keras untuk ini dan tak berasa hingga 4 tahun lamanya pergulatan itu berlangsung. Saya sudah menjadi kebal dengan omongan dari keluarga dan orang lain yang mengatakan saya terlalu idealis dan lain sebagainya. Walaupun begitu, perjuangan ini akhirnya berbuah juga. Kaget sebenarnya ketika skripsi saya selesai dengan jumlah total 737 halaman. Kalau dihitung 1 halaman per hari, maka ini menghabiskan waktu 737 hari atau 2 tahun waktu penulisan. Yang 2 tahun lagi, waktunya dipakai untuk melakukan pencarian referensi, membaca, dan berdiskusi. Yang jadi masalah, saat hendak menyampaikan untuk ujian, saya harus mencari tempat Fotokopi besar karena yang lain tidak sanggup untuk melakukan penjilidan setebal itu. Hanya satu tempat Fotokopi, yang ada di depan Mirota Kampus, yang sanggup menerima dan mengerjakannya. Jadilah skripsi buntelan ini saya bawa untuk maju ujian dan, akhirnya, lulus juga. [ 😀 ]
Berjejaring hingga ke Singapura dengan Dr. Syam Surya
Empat belas tahun berlalu, saya sedang menempuh studi Doktor di Universitas Indonesia saat saya pertama kali bertemu dengan Dr. Syam Surya. Kami waktu itu sama-sama menjadi asisten pengajar Filsafat Ilmu dan Pendekatan Pascadisiplin yang diampu oleh Dr. Akhyar Yusuf Lubis. Beliau ini mengajak saya untuk mendirikan lembaga yang disebut dengan Sakola (sekolah, dalam bahasa Sunda) bersama Dr. Akhyar Yusuf Lubis. Tadinya, ini direncanakan untuk berisi semacam kursus bidang Filsafat dan yang lainnya. Namun, dalam perjalanannya, hal ini melibatkan juga yang lain, yaitu pendidikan alternatif Home Schooling untuk tingkat SMP dan SMA.
Pada awal perjalanan, saya dipasrahi untuk memikul tanggung jawab sebagai Direktur Center of Digital Excellence (CoDE), suatu lembaga semi otonom di bawah naungan Sakola. Tugas saya juga merangkap sebagai duta Kecerdasan Digital (Digital Quotionent) dari program yang diselenggarakan oleh DQ Institute yang ada di Singapura. Hal ini cukup mengesankan dan menyenangkan karena bidang pekerjaan ini sesuai dengan apa yang telah kaji semasa saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada. Kami pun bahu membahu menyelenggarakan pelatihan soal Kecerdasan Digital ini untuk tingkat pendidikan dasar/menengah dan para orangtua di berbagai sekolah daerah Tangerang, Jakarta, hingga Surabaya, di antaranya sekolah B.P.K. Penabur (Bogor), Tzu Chi International School (Pantai Indah Kapuk), bank OCBC NISP (Jakarta & Surabaya), Yayasan Penabur (Jakarta), Atisa Dipamkara (Tangerang), Tarakanita (Gading Serpong), B.P.K. Penabur (Gading Serpong), dan Stella Maris International School (Gading Serpong). Selain di sekolah ini, kami bekerjasama juga menyelenggarakan pelatihan Kecerdasan Digital bersama Universitas Prasetya Mulya dan Universitas Pelita Harapan.
Kecerdasan Digital yang disusun oleh DQ Institute cukup komprehensif dan praktis untuk diterapkan di berbagai pendidikan dasar dan menengah. Untuk pendidikan tinggi, hal ini memerlukan penyesuaian dan rencananya sudah masuk dalam pengembangan kurikulumnya di tahun 2019. Di tahun 2020, Kecerdasan Digital yang mereka susun sudah disetujui menjadi standar dalam satu komponen Keterampilan Digital (Digital Skills) dari asosiasi para Insinyur Elektro di Amerika, yaitu IEEE. Mereka memasukkan Kecerdasan Digital sebagai standar kompetensi dengan nomor IEEE 3527.1-2020 atau IEEE Standard for Digital Intelligence (DQ) Framework for Digital Literacy, Skills, and Readiness. Dengan cara ini, Kecerdasan Digital menjadi prasyarat kompetensi lainnya yang diperlukan untuk dapat disebut “piawai” dalam dunia digital.
Sayangnya, pekerjaan ini pada akhirnya saya lepas dengan keputusan saya sendiri karena saya mendapat tugas dari kampus Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya sebagai Direktur Pascasarjana. Tentu saja ada rasa sedikit kecewa karena tidak dapat berkarya lagi untuk mengembangkan Kecerdasan Digital. Meskipun begitu, rasa kekecewaan saya ini segera terpupus begitu Pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Bukannya apa-apa, kriteria dan segala aspek yang berkenaan dengan Kecerdasan Digital yang dibangun oleh DQ Institute menjadi hampir “tak berguna” sama sekali karena semua pelajaran sekolah di Indonesia, dari tingkat TK hingga Universitas diberikan secara daring. Praktik ini tentu saja melanggar kriteria untuk akses gawai maksimal selama 2-5 jam sesuai yang ditetapkan dalam kategori Waktu Tatap Layar (Screen Time Management) sebagai salah satu kompetensi Kecerdasan Digital.
Selain itu, apa yang disebut dengan Kecerdasan Digital itu sendiri, jika masih menggunakan kriteria yang lama, tentu saja akan mengalami problematikanya sendiri mengingat kehidupan pasca Pandemi COVID-19 akan mengubah banyak hal. Kemungkinan paling besar adalah pergeseran yang cepat dari dunia digital ke dunia hibrid yang lebih kompleks. Yang perlu disiapkan oleh kita adalah keterampilan adaptif yang lebih fleksibel pada kompleksitas daripada sekadar kriteria atau standar yang ditentukan secara tertentu/terukur. Atau, di masa depan, situasinya akan membuka kemungkinan bagi kita untuk meningkatkan kapasitas tanpa perlu bersusah payah dengan proses pembelajaran tradisional melalui metode penalaan manusia (human enhancement) karena teknologinya sudah akan lebih siap secara penuh dalam satu dasawarsa. Jika Indonesia memang berniat mengadopsi Kecerdasan Digital, ya ini hanya akan bertahan sejauh itu. Meskipun dalam laporan 2020 Child Online Safety Index tahun 2020 yang dikeluarkan oleh DQ Institute posisi Indonesia ada jauh di level bawah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kita dapat mengatasinya dengan cara lain yang lebih impresif dan tak terduga asalkan kita terus berupaya untuk itu.
Bogor, 23 Januari 2021
Unduh artikel/esai ini dalam bentuk pdf